 |
| sumber foto: pixabay.com |
F. Budi Hardiman dalam bukunya, Seni Memahami: Hermeneutik dari Schleirmacher sampai Derrida (Kanisius, 2015) menjelaskan bahwa tidak memahami juga bagian dari pemahaman. Ungkapan seperti, “Saya tidak paham dengan dirimu”, menunjukkan bahwa sebenarnya saya melakukan tindakan memahami dengan cara tidak memahami.
Ketidakmungkinan saling memahami itulah yang membuat status ini sangat penting bagi peradaban manusia yang hendak dan/atau sedang pacaran. Hal yang sama dijelaskan oleh Paul Verhaeghe dalam esainya bertajuk “From Impossibility to Inability: Lacan’s Theory on the Four Discourses” dalam Does the Woman Exist (1995) tentang bagaimana Lacan mendefinisikan komunikasi secara negatif.
Verhaeghe menulis bahwa umumnya tujuan utama dari teori komunikasi yakni membawa komunikasi kepada standar yang sempurna dengan cara menghilangkan segala sesuatu yang ribut (noise) agar pesan bisa dengan bebas mengalir antara sender dan resipien. Namun Jacques Lacan memulai teori komunikasinya dengan asumsi bahwa komunikasi senantiasa gagal. Mengutip Lacan, Verhaeghe menulis,
bagaimana pun juga komunikasi mesti gagal dan karena alasan itulah mengapa kita tetap terus berbicara. Jika kita saling memahami, kita akan diam. Cukup beruntung, kita tidak saling memahami sehingga kita harus berbicara satu dengan yang lain.
Bagi Lacan, jika komunikasi konvensional mereduksi berbicara sekadar pada konsensus maka hal itu justru melenyapkan status ketidaksadaran. Dengan menganjurkan wacana histeris (sebagai lawan dari wacana akademis), ketidaksadaran bukan hanya berbicara, tetapi seperti kata Lacan dalam aksioma, the unconscious is structured as a language.
 |
| ilustrasi |
Pernyataan provokatif di atas, secara tidak langsung ingin menunjukkan bahwa penciptaan pelbagai platform media sosial misalnya, tidak akan pernah secara purna menjawabi kebutuhan manusia untuk berkomunikasi. Dikatakan demikian karena dalam diri setiap subjek terdapat apa yang disebut Lacan sebagai abyss. Sebuah jurang atau gap yang tidak terjembatani. Atau mengutip Aan Mansyur, jurang antara kebodohan dan keinginanku untuk memilikimu sekali lagi.
Jurang itu pula yang menyebabkan kapitalisme dan komodifikasi tidak pernah berhenti bermetamorfosis. Jurang yang sama itu pula yang membuat mantan membiak bagai jamur di samping kapitalisme menjelma serupa vampir. Tepat pada level itulah, manusia tetap setia menjaga mulutnya agar tidak berhenti berbicara dan merawat jempolnya untuk berkanjang dalam menulis komentar.
Saya menduga, ini pula alasannya mengapa perkawinan bukanlah cara yang paling tepat bagi tumbuh dan berkembangnya kebahagiaan. Demikian pula pacaran yang secara konvensional cenderung dianggap sebagai salah satu dari sekian tahapan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan.
Alih-alih fokus pada upaya membangun keluarga dalam perkawinan atau merawat cinta dalam pacaran, psikoanalisa justru menaruh perhatian pada aktivitas ‘menyimpang’ seperti perselingkuhan dan niat untuk putus. Alih-alih fokus pada rasionalitas, psikoanalisa fokus pada ketidaksadaran. Alih-alih fokus pada upaya menjadi subjek yang otonom, psikoanalisa fokus pada kegagalan menjadi subjek.
Dengan kata lain, psikoanalisa berupaya membahas hal yang tidak dibicarakan atau berusaha dihindarkan orang kebanyakan yakni situasi kekelaman, kerentanan, dan kerapuhan sang subjek. Melalui kondisi seperti itulah, proses pembentukan subjek dimungkinkan mengingat tanpa ada kekurangan dan kerentanan dalam term psikoanalisa dan mukjizat dalam term teologis, cinta sejati mustahil terwujud.
Dalam karyanya berjudul Emile or On Education, Jean-Jacques Rousseau menulis tentang perkembangan manusia, khususnya melalui pendidikan, untuk mencapai standar-standar reason dan intellect. Pendidikan tahap terakhir mengajarkan tentang sosialisasi, pertemanan, agama, dan seks. Tentu Emile, tokoh utama buku Rousseau itu, membutuhkan teman yang “pantas” agar bisa menjadi manusia yang seutuhnya, mandiri dan bebas. Namun, teman bagaimanakah yang “pantas”? Pemutlakan pada akal budi seperti inilah yang membuat pembahasan cinta dan hasrat di abad modern, yang tertuang dalam pemikiran Rousseau, Descartes, Hume atau Kant, tampak membosankan.
Berbanding terbalik dengan hal di atas, Jacques-Alain Miller dalam book chapter-nya On Semblances in the Relation between Sexes (2000) menunjukkan bagaimana pembacaan Lacan terhadap Tragedi Medea karya Euripides. Medea ditulis dengan mengambil latar Athena 413 SM. Tragedi ini mengisahkan kehidupan perempuan bernama Medea, suaminya Jason, dan anak-anak mereka.
Sebagai seorang istri dan perempuan, Medea sudah memenuhi semua kewajibannya. Demi menikah dengan Jason, Medea telah mengkhianati ayah dan bangsanya, bahkan secara tidak langsung dengan menggunakan tenaga Pelia, ia telah membunuh ayahnya sendiri. Akibatnya, Medea harus rela hidup dalam pengasingan di Korintus bersama suami dan anak-anaknya. Untuk sesaat, perkawinan Jason dan Medea berlangsung tanpa pertikaian apa pun.
Tragedi dimulai di suatu hari, manakala Jason menyampaikan niat mengawini seorang perempuan lain, putri Creon. Medea sama sekali tidak bisa menerima niat Jason. Tetapi suaminya tetap berkeras hati. Medea mengalami depresi. Ia kehilangan daya hidup dan meratapi diri setiap malam. Di ujung ratapannya, meluncurlah ungkapannya yang legendaris:
Of all living things which are living and can form a judgment
We woman are the most unfortunate creatures…
Jason mencoba membujuk Medea dengan menawarkan segala ‘kebaikan’ dan jaminan bagi hidup Medea dan anak-anaknya. Jason berjanji tidak akan menelantarkan mereka. Tapi, Medea tetap tidak bisa menerima ‘kebaikan’ Jason. Baginya, begitu Jason mencintai perempuan lain, maka ‘memiliki’ tidak lagi bermakna apa pun.
Medea memutuskan membalaskan sakit hatinya kepada Jason. Tapi ia tidak ingin membunuh Jason. Baginya, itu akan terlampau sederhana dan tak akan pernah bisa mengembalikan lagi apa yang telah rusak dan terenggut dari dirinya. Ia memilih mencari titik paling memilukan bagi kehidupan suaminya. Maka ia memutuskan untuk membunuh pengantin suaminya dan anak-anaknya sendiri.
Melalui kisah di atas, Euripides berupaya menunjukkan nilai moral dari tindakan ekstrem dengan menggambarkan rasa sayang Medea sebagai ibu kepada anak-anaknya di saat-saat terakhir memilukan kehidupan anak-anak itu. Bagaimana Medea berbisik lirih di telinga anak-anak itu; bagaimana ia mendongengkan kembali siapa dirinya, siapa mereka, dan apa sesungguhnya harapan-harapan terbaiknya kepada mereka, sebelum akhirnya secara mengerikan membunuh anak-anaknya.
Di titik inilah, seorang perempuan melampaui dirinya sebagai seorang ‘ibu’. Melalui tindakan itu, Medea menjejakan sebuah contoh apa artinya menjadi perempuan dengan menanggalkan dan memutuskan semua sistem simbolik (the Symbolic), termasuk simbol sebagai ibu. Melalui tindakan ini ia keluar dari depresi. Seluruh dirinya adalah tindakannya. Setelah tindakan itu, semua kata-kata adalah sia-sia.
Dalam pandangan Lacan, Medea, pada situasi di mana ia sudah tidak lagi memiliki apa pun untuk membela dirinya, menemukan senjata maut untuk mengalahkan Jason. Senjata maut itu adalah dengan ‘memotong’ bagian paling berharga dari dirinya, yakni anak-anaknya.
Pada akhirnya, tindakan Medea merupakan tindakan menunda hukum, moral, tatanan sosial dan mengingatkan saya pada pembelaan Arendt terhadap komandan Nazi, Adolf Eichman, atau Paus Yohanes Paulus II yang memaafkan penembaknya, dan Yesus Kristus yang menjanjikan firdaus bagi penyamun.
Arendt, Paus, Medea, dan Yesus mengajarkan upaya melampaui serentak menunda the Symbolic. Sebab hanya dengan berani katakan putus, Anda sedang berusaha menjadi subjek yang otentik. Subjek yang tidak bergantung total pada tatanan sosial-politik di luar diri.
Meskipun seperti dialektika Hegel (tesis, antitesis, sintesis, antitesis, dan seterusnya) di mana mengatakan putus pada yang satu mengantar Anda memasuki tatanan the Symbolic yang lain, sekurang-kurangnya Anda telah belajar melawan. Bukan soal Anda kalah atau menang melainkan belajar menemukan sesuatu di dalam dirimu. Mengutip Lacan, ada sesuatu di dalam dirimu lebih dari sekadar dirimu (something in you more than you).
“Kita kalah, Ma,” kata tokoh Minke pada bagian akhir novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. Namun, sesaat sebelum punggung kereta yang ditumpangi Annelies menghilang, dengan nada berwibawa, Nyai Ontosoroh membalas, “Kita telah melawan, Nak, Nyo, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.”
Resistensi serupa juga diucapkan oleh Sekretaris Negara AS, Ruth McMillan (diperankan oleh Melissa Leo) dalam film Olympus Has Fallen (2013) yang disutradarai oleh Antoine Fuqua.
Usai disiksa oleh teroris bernama Kang, dengan nafas tersenggal, Ruth mengatakan kepada Presiden AS, Benjamin Asher (diperankan oleh Aaron Eckhart),
Kita mungkin menemui Pencipta kita hari ini. Tapi satu hal yang tak kumau ada di batu nisanku: Dia mati tanpa perlawanan.




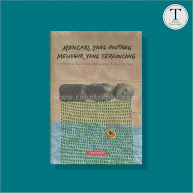
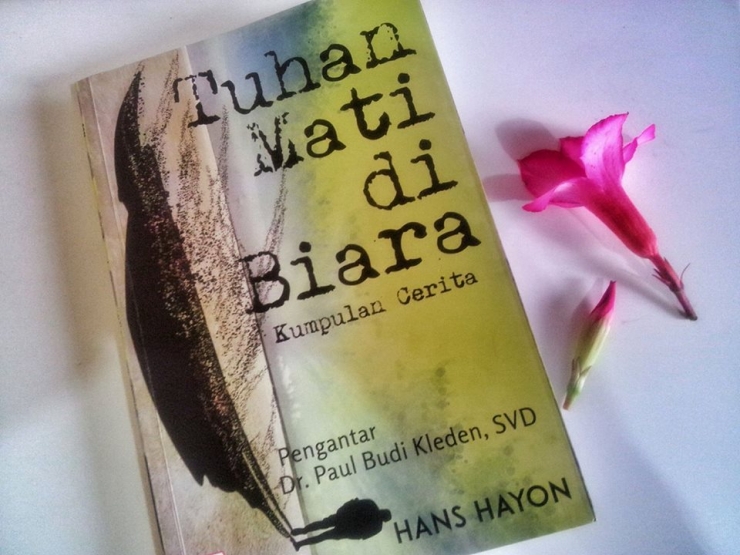

Post a Comment
Post a Comment