Sebelum menjelaskan tentang bagaimana konsep metafora dan metonimi digunakan untuk menjelaskan fenomena aphasia, pertama-tama terlebih dahulu dideskripsikan secara singkat mengenai konsep metafora dan metonimi.
Selanjutnya, dari sudut pandang Roman Jakobson, saya berupaya menjelaskan bagaimana Jakobson menggunakan dua konsep tersebut untuk menganalisis fenomena apasia.
Tentu saja, penjelasan ini didahului oleh definisi dan gambaran singkat mengenai aphasia dan bagaimana pendekatan linguistik berperan dalam menangani masalah tertsebut.
Pertama, metafora dan metonimi
Membincangkan dikotomi metafora dan metonimi dalam konteks ini mengisyaratkan adanya kesalingkterkaitan dengan pembedaan lain yang dibuat oleh Ferdinand de Saussure. Saussure menegaskan bahwa hubungan sintagmatik dan asosiatif berkaitan dengan dua bentuk aktivitas mental, dan ini berarti meluas hingga keluar dari linguistik.
Jakobson mengadopsi perluasan tersebut dengan menerapkan oposisi antara metafora (yang merupakan ranah sistematik) dan metonimi (ranah sintagmatik) pada bahasa non-linguistik (Barthes, 2012: 57).
Dalam bukunya berjudul Linguistics and Poetics, Roman Jakobson menyebutkan bahwa metafora berfungsi sebagai media pengungkapan perasaan manusia misalnya rasa sedh, gembira, marah, kesal, dan sebagainya. Fungsi tersebut juga bisa disebut sebagai fungsi emotif (Jakobson, 1960:4).
Jakobson mengadopsi perluasan tersebut dengan menerapkan oposisi antara metafora (yang merupakan ranah sistematik) dan metonimi (ranah sintagmatik) pada bahasa non-linguistik (Barthes, 2012: 57).
Metafora juga berfungsi sebagai penyampai pesan atau amanat tertentu, pengungkapan gagasan, perasaan, kemauan, dan tingkah laku seseorang. Fungsi ini disebut juga dengan fungsi puitik (Jakobson: 1960:17).
Meskipun fungsi metafora yang dipahami di atas muncul dari proses pembacaannya terhadap literatur khususnya puisi, bagi Jakobson, metafora bergantung pada sumbu paradigma sedangkan metonimi bergantung pada sumbu sintagma; keduanya mewakili dua prosedur yang berbeda: prosedur yang pertama adalah penggantian dengan kemiripan dan yang kedua penggantian dengan kontinguitas/hubungan (Eco, 2009: 418). Secara sederhana, penjelasan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
Meskipun fungsi metafora yang dipahami di atas muncul dari proses pembacaannya terhadap literatur khususnya puisi, bagi Jakobson, metafora bergantung pada sumbu paradigma sedangkan metonimi bergantung pada sumbu sintagma; keduanya mewakili dua prosedur yang berbeda: prosedur yang pertama adalah penggantian dengan kemiripan dan yang kedua penggantian dengan kontinguitas/hubungan (Eco, 2009: 418). Secara sederhana, penjelasan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
Metafora = Substitusi: kondensasi atau penyingkatan
Metonimi = Kombinasi: pemindahan
Dengan bahasa lain, ranah metaforis mengandaikan asosiasi melalui substitusi sebagai proses yang dominan dan ranah metonimi mengandaikan asosiasi sintagmatik sebagai proses yang dominan.
Mengenai hal yang sama, dalam bukunya Fundamentals of Language, Jakobson berbicara tentang dua aspek cara penetapan tanda yakni kombinasi dan seleksi (termasuk substitusi). Ketika ingin memproduksi makna dalam rangka berkomunikasi, orang mesti akan menggunakan dua cara: kombinasi dan seleksi (Jakobson, 1956:60).
Mode seleksi muncul dengan adanya similarity/continuity. Bagi Jakobson, kualitas seleksi/substitusi bertepatan dengan ide tentang metafora, yang mana beberapa kesamaan sebuah penanda dapat digunakan untuk menunjuk (atau menggantikan) yang lain.
Mode kombinasi, sebaliknya, berfungsi untuk menggabungkan unit makna yang berbeda secara bersama dengan menempatkan mereka dalam konteks yang sama, dan muncul dengan implikasi tentang perbedaan, diskriminasi, hubungan, dan pemindahan.
Jakobson berargumen bahwa gagasan ini sangat dekat dengan metonimi sejak bukan “kesamaan” dari dua penanda yang mengasosiasikan mereka tetapi hubungan (contiguity) mereka, secara sintaksis, atau kedekatan fisikal dan kontekstualitas.
Kedua, aphasia
Oxford English Dictionary (Eleventh Edition) mendefinisikan aphasia sebagai inability to understand or produce speech as a result of brain damage. Dari definisi umum seperti ini, otomatis penanganan terhadap penyakit tersebut dengan bantuan ahli saraf otak misanya.
Kecenderungan akan penanganan medis seperti ini dan mengabaikan disiplin ilmu lain, menggelisahkan Jakobson, terutama dalam Aphasia as A Linguistic Problem. Di dalam chapter tersebut ia menjelasakan bahwa aphasia merupakan masalah masa kanak-kanak, yang selama ini pemecahannya membutuhkan koordintasi lintas disiplin dan kerja sama dengan para ahli tentang penyakit pada pendengaran dan kerongkongan, dokter anak, ahli pendengaran, psikiater, dan para intelektual tetapi para ahli bahasa dibaikan.
Meskipun diakui bahwa aphasia itu merupakan gangguan persepsi dalam berbicara tetapi tidak ada yang dilakukan dengan pendekatan linguistik. Sebaliknya, Jakobson menawarkan proses pemecahan terhadap gangguan berbahasa (aphasia) berdasarkan pendekatan linguistik melalui beberapa tahapan yakni: linguis hendaknya familiar dengan istilah teknis dan perangkat-perangkat disiplin medis yang berkaitan dengan apasia, selanjutnya, mengajukan laporan-laporan masalah klinis melalui analisis linguistik, dan terakhir hendaknya bekerja bersama pasien apasia dalam rangka mendekati kasus secara langsung dan bukan hanya melalui re-interpretasi terhadap data yang sudah tersedia (Jakobson, 1956:56).
Similarity Disorder
Bagi penderita aphasia tipe pertama dengan gangguan pada seleksi, konteks merupakan faktor yang sangat diperlukan dan paling menentukan. Pasien aphasia jenis ini cenderung berbicara reaktif: ia mudah terlibat dalam percakapan tetapi sulit memulai sebuah dialog. Semakin banyak ucapannya bergantung pada konteks, semakin baik ia mengulang dengan ucapan verbal. Contohnya, kalimat “sedang hujan” tidak bisa dibuat kecuali kalau pengucapnya melihat bahwa memang benar-benar sedang hujan (Jakobson, 1956: 63).
Dalam teori tentang bahasa sejak awal Abad Pertengahan yang menegaskan bahwa kata yang berada di luar konteks sama sekali tidak memiliki makna, bagaimana pun juga khusus untuk aphasia teristimewa aphasia tipe pertama (Jakobson, 1956: 64). Sejak kata-kata khusus memiliki jumlah informasi yang lebih tinggi daripada homonimi, beberapa aphasis dengan tipe ini menambahkan konteks yang berbeda dari sebuah kata dengan istilah berbeda, masing-masing kata khusus untuk lingkungan yang ditampilkan.
Mereka tidak pernah menyebut kata “pisau” secara otonom melainkan berdasarkan penggunaannya, seperti pisau untuk meruncingkan pensil (pencil-sharperner), pisau roti (bread-knife), pisau dan garpu (knife-and-fork). (Jakobson, 1956: 65).
Kembali ke pembagian dikotomis antara metafora dan metonimi, pasien aphasia (atau sakit paradigmatic) dengan gangguan similarity disorder dapat dibantu dan dipahami melalui metafora yang menggunakan prosedur penggantian dengan kemiripan.
Di sini, pasien dibantu untuk melakukan seleksi/substitusi guna menemukan kesamaan sebuah penanda yang dapat digunakan untuk menunjuk (atau menggantikan) yang lain.
Contiguity Disorder
Bagi penderita aphasia tipe kedua dengan gangguan contiguity disorder dapat dipahami melalui metonimi. Gangguan ini bisa disebut sebagai sakit sintagmatik yakni hilangnya kemampuan mengorganisasi kata secara sintagtik kedalam sebuah unit yang lebih tinggi (Jakobson, 1956:72). Susunan kata menjadi kacau-balau. Di sini, pasien memang mudah memahami, mengulang dan secara spontan mengucapkan kata tertentu namun tidak bisa memahami dan mengulang rangkaian yang bukan-bukan.
Oleh sebab itu, pasien dengan gangguan contiguity dapat dibantu melalui metonimi di mana kata yang berasal dari akar kata yang sama secara semantik dikaitkan melalui hubungan.
Ini disebut dengan mode kombinasi yakni menggabungkan unit makna yang berbeda secara bersamaan dengan menempatkan mereka dalam konteks yang sama.
Ketiga, Wacana Histeris dan Universitas
Mengapa Lacan lebih memilih wacana histeris daripada wacana universitas sebagai model pengetahuan?
Sebelum membahas tentang konsep wacana menurut Lacan, pertama-tama akan dijelaskan mengenai titik tolak di mana konsep tersebut muncul yakni tindakan komunikasi. Sebagaimana yang diketahui umum, komunikasi mengandaikan adanya relasi sosial sebagai sebuah conditio sine qua non. Tujuan utama dari teori komunikasi yakni membawa komunikasi kepada standar yang sempurna dengan cara menghilangkan segala sesuatu yang ribut (noise) agar pesan bisa dengan bebas mengalir antara sender dan resipien (Paul Verhaeghe, 1995).
Lacan memulai teori komunikasinya dengan asumsi bahwa komunikasi senantiasa gagal: bagaimana pun juga komunikasi mesti gagal dan karena alasan itulah mengapa kita tetap terus berbicara. Jika kita saling memahami, kita akan diam. Cukup beruntung, kita tidak saling memahami sehingga kita harus berbicara satu dengan yang lain (Ibid.). Pelbagai wacana menjangkau sejumlah tema sejauh ketakmungkinan komunikasi terjadi. Tentu saja hal konsep ini berbeda dengan teori wacananya Foucault yang menitik beratkan pada isi wacana; sedangkan Lacan, sebaliknya, melampaui isi dan tempat terjadinya wacana di atas relasi formal bahwa setiap wacana dipahami melalu aksi berbicara.
Bagi Lacan, wacana adalah hubungan sosial, seperangkat kekuasaan yang dinamis, sebuah cara mengartikulasikan relasi antara ego, pengetahuan, apa yang tidak bisa diketahui, dan apa yang dihasrati. Sebuah wacana meliputi empat struktur yang terdiri atas:
Pertama, agen atau speaker yang merupakan sumber dari beberapa iven diskursif partikular. Kedua, the other atau audiens. Ketiga, the truth atau pesan yang mungkin speaker miliki dan kirim. Keempat, makna yang audiens bangun dari pesan, yang oleh Lacan disebut sebagai “produksi”. (T.R. Johnson, 2014:105).
Berdasarkan empat struktur di atas, Lacan lalu memperkenalkan empat jenis wacana (Discourse of the master, University discourse, Analytic discourse, dan Hysteric’s discourse) tetapi dalam tulisan ini saya coba menjelaskan alasan mengapa Lacan lebih memilih wacana histeris daripada wacana universitas sebagai model pengetahuan.
Semua ini dilakukan dalam rangka menunjukkan objek, a yang tidak pernah seutuhnya terpuaskan. Sebagai misal, kita menulis tesis untuk memenuhi standar kelulusan yang ditetapkan oleh IRB Sanata Dharma, lalu diwisuda sebagai magister, lalu berharap bisa bekerja di lembaga tertentu, lalu meraih penghargaan sebagai intelektual public, dan seterusnya. Artinya, objek-a selalu merupakan harapan yang selalu diperbaharui, tidak peduli apa yang sudah kita capai.
Nah, upaya subjek (kita) untuk mengisi objek-a selalu memproduksi $, pengalaman keterbelahan subjek yang secara kasar dapat diformulasikan sebagai ketegangan antara apa yang diharpakan (das Sollen) dan yang senyatanya (das Sein). Saya lulus dari UGM tetapi itu adalah sebuah kekeliruan, saya seorang magister tetapi orang lain menunjukkan betapa kerja ilmiah yang saya lakukan itu salah. Semuanya ini dipengaruhi oleh kebiasaan untuk membaca banyak buku, berpikir mendalam dan tidur telat dini hari.
Dengan kata lain, wacana universitas memproduksi subjek yang mungkin sulit tidur karena ada gap antara apa yang tampak dan “realitas” ($). Itulah alasan mengapa subjek yang berbicara sebagai S2 pada Hegel berarti berbicara sebagai budak; tetapi pada Lacan, S2 merujuk pada “pengetahuan”. Tentu saja, wacana universitas sebagaimana yang dijelaskan di atas, bukan seperti yang dipahami oleh David Bartholomae sebagai “wacana akademis” (T.R. Johnson, 2014:137). Sebaliknya, wacana jenis ini lebih cocok dianggap sebagai wacana birokratis, sistem.
Di samping ada wacana universitas, terdapat wacana lain yang digunakan oleh Lacan yakni wacana histeris. Ketika praktisi medis dan psikoanalisis bergerak maju dari histeria sebagai sebuah diagnosa dan mengklaim bahwa itu sebagai sebuah fenomena aktual, ilmuwan dan teoretisi dalam akademi humaniora memberikan daya baru, karena histeria menawarkan sebuah cara yang luar biasa untuk mulai mendiskusikan tentang gender dan kebudayaan, seksualitas dan kebertubuhan, bahkan semua domain representasi dan performativitas. Singkatnya, histeria merupakan revolusi retorik tubuh. Karena histeria merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari, setiap manusia itu semuanya histeris (T.R. Johnson, 2014:168).
Implikasinya jelas yakni jika pada wacana universitas, agen atau penulis menulis dari sebuah sistem pengetahuan, pokok informasi, yang kemudian disebut sebagai S2, sedangkan pada wacana histeris agen atau penulis, menulis dari sebuah ketidaksadaran, yang disebut sebagai $ (T.R. Johnson, 2014:106). Posisi agen yang diambil oleh ketidaksadaran, $ yang dapat digambarkan sebagai berikut:
Tanda $ menggambarkan subjek ketidaksadaran yakni subjek yang tunduk pada hukum ketidaksadaran. Jadi, istilah $, subjek, dan ketidaksadaran, digunakan secara bergantian. Di sini, kita bisa menambahkan istilah lain yakni hasrat (desire). $ inilah yang menjadi penanda hasrat yang tidaksadar, yang memedakan subjek dari individu, dan menghubungkan setiap orang dalam relasi penanda intersubjektivitas. Ketidaksadaran bukan hanya berbicara, tetapi seperti kata Lacan dalam aksioma, the unconscious is structured as a language (T.R. Johnson, 2014:98).
Tanda $ menggambarkan subjek ketidaksadaran yakni subjek yang tunduk pada hukum ketidaksadaran. Jadi, istilah $, subjek, dan ketidaksadaran, digunakan secara bergantian. Di sini, kita bisa menambahkan istilah lain yakni hasrat (desire). $ inilah yang menjadi penanda hasrat yang tidaksadar, yang memedakan subjek dari individu, dan menghubungkan setiap orang dalam relasi penanda intersubjektivitas. Ketidaksadaran bukan hanya berbicara, tetapi seperti kata Lacan dalam aksioma, the unconscious is structured as a language (T.R. Johnson, 2014:98).
Sebagaimana bagan di atas, penanda utama atau ego (S1) memproduksi pengetahuan (S2) dalam rangka menjelaskan perilaku histeria, menjawab pertanyaan-pertanyaannya, menarik hasil signifikasi ini sejauh mungkin kembali kedalam kode-kode wacana rasional (misalnya, wacana tentang universitas dan otoritas kekuasaan). Masing-masing wacana berubah bergantung dari lokasi di mana ketidaksadaran ditempatkan. Pada wacana universitas, disebut sebagai “produksi” sedangkan pada wacana histeris disebut sebagai subjek yang berbicara. Dikatakan demikian karena struktur histeria bersifat laten dalam diri semua manusia dan berkembang ketika kita berbicara dari keterpecahan atau keterbelahan subjektivitas, $. (T.R. Johnson, 2014:169).
Dari penjelasan di atas, secara singkat dapat dikatakan bahwa beberapa alasan mengapa Lacan lebih memilih wacana histeris daripada wacana universitas antara lain:
Pertama, wacana histeris lebih representatif dalam menggambarkan model pengetahuan subjek yang otentik sedangkan wacana universitas justru merepresi subjek yang otentik tersebut.
Kedua, pada wacana histeris, yang berbicara adalah subjek yang terbelah/terbagi yang memiliki hasrat sedangkan pada wacana universitas, subjek tidak memiliki otoritas atau kuasa karena ia tunduk pada sistem tertentu.
Ketiga, wacana histeris hendaknya menjadi jalan di mana pribadi neurotic saling berhubungan dengan orang lain. Dikatakan demikian karena pada wacana ini, subjek selalu membawa kekurangan (lack) konstitutif di dalam dirinya. Sementara itu, pada wacana universitas, lack konstitutif tersebut direpresi dan direduksi oleh sistem yang memuja otonomi subjek. Artinya, wacana universitas tampil sebagai, sebut saja narasi besar, yang menghidupi ilusi kepenuhan dan keutuhan subjek.
Daftar Pustaka
Umberto Eco, (terj.)Teori Semiotika (Signifikasi Komunikasi, Teori Kode, serta Teori Produksi Tanda)Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009.
Roman Jakobson, Fundamental of Language, Netherlands: Mouton & Co, 1956.
Micahel Georg Herteis, Roman Jakobson’s Poetic Function of Language; The Historic Theory of Equivalence Projections from the Axis of Selection into the Axis of Combination (dissertation), Faculty of the Graduate School, University of Southern California, Desember 1998.
Roman Jakobson, Child Aphasia and Phonological Universals, Netherlands: Mouton Publisher, 1968.
Roland Barthes, Elemen-Elemen Semiologi, Yogyakarta: Jalasutra, 2012.
Roman Jakobson, “ Linguistics and Poetics”, Makalah yang dipresentasikan di Indiana University, musim semi 1958, dan direvisi dan dipublikasikan dalam Style in Language, (ed). Thomas A. Sebeok, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1960
T.R. Johnson, The Other Side of Pedagogy, Lacan’s Four Discourses and the Development of the Student Writer, New York: State University of New York, 2014.





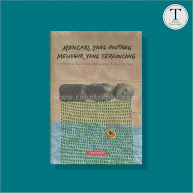
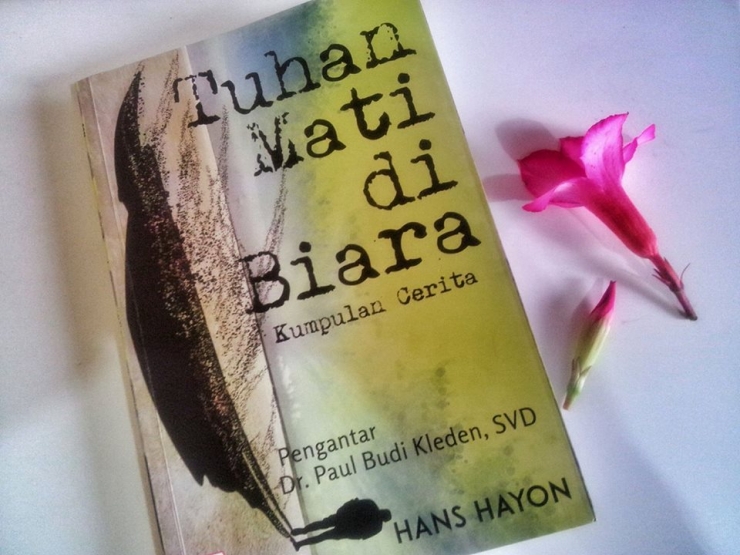

Post a Comment
Post a Comment