Mengapa demikian? Ya, karena saya justru mengkritik hal tersebut, terutama karena solusi yang dihasilkan selalu tidak masuk akal dan berupaya mengindari pembahasan terkait akar penyebab. Artinya, antara sebab dan akibat selalu bertukar tempat.
Pertama, solusi yang ditawarkan tidak masuk akal. Kolom opini Tempo 27 November 2022 menulis bahwa Konferensi COP27 di Sharm el-Seikh Mesir menaikan target pembiayaan negara maju dari 100 miliar dollar Amerika tahun lalu menjadi 134 miliar dolar tahun depan. Kesepakatan itu diulang-ulang oleh Sekretaris Jenderal UN Antonio Guterres mengajak untuk menetapkan pajak yang lebih besar bagi perusahan industri fosil untuk meningkatkan pendanaan (Aljazeera.com, 20 November 2022).
Namun, masalahnya bukan di situ. Jika kita bicara tentang keadilan iklim, itu tidak sama dengan penebusan gas rumah kaca seperti perdagangan karbon. Sebaliknya, keadilan iklim adalah konsep yang menghadang pemanasan global dari sumbernya. Mengapa? Ya karena skema perdagangan karbon dan pembiayaan dari kesepakatan COP27, memberikan jalan keluar bagi produsen emisi untuk mencuci dosa lingkungan mereka (atau greenwashing) dengan membeli penyerapan karbonnya di tempat lain. Perdagangan karbon, jika hanya menukar emisi, memang menjadi tidak adil. Negara-negara dan industri kaya akan terus memompa gas rumah kaca sementara penyerapannya ada di negara tropis yang miskin. Transaksi dari negara kaya ke negara miskin kian menunjukkan ketimpangan dalam mitigasi krisis iklim yang ingin mencegah pemanasan global.
Selanjutnya, kesepatakan COP27 yang dihasilkan pun tidak jelas karena belum memberi kepastian terkait negara berkembang yang mendapat dana bantuan itu atau pedoman pendanaan yang bisa dijadikan sebagai panduan.
Selanjutnya, kesepatakan COP27 yang dihasilkan pun tidak jelas karena belum memberi kepastian terkait negara berkembang yang mendapat dana bantuan itu atau pedoman pendanaan yang bisa dijadikan sebagai panduan.
Tidak berhenti di situ, kesepakatan seperti itu justru berbanding terbalik dengan proyek strategis dalam negeri yang masih mengizinkan penggunaan batu bara. Inkonsistensi ini makin terlihat ketika pemerintah mengabaikan keputusan MK dengan terus menjalankan klausul-klausul dalam UU Cipta Kerja.
Hal itu bisa kita amati misalnya melalu kritikan yang disampaikan oleh pegiat lingkungan yang tergabung dalam Green Peace yang menggelar aksi dalam forum G20 di Bali. Pesan utama yang merak sampaikan yakni bahwa Indonesia justru tidak konsisten menerapkan transisi energi sebab dalam Rencana Umum Pengadaan Tenaga Listrik (RUPTL), Indonesia masih akan menggunakan batu bara, pararel dengan phase out secara bertahap hingga tahun 2056. Bagian paling ironis dari itu adalah bahwa mayoritas negara G20 merupakan penyumbang emisi terbesar yakni hampir 80 persen dari emisi global.
Bagian paling lucu dari semuanya itu disampaikan oleh Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak, Senin (21/11) bahwa ini menandakan keengganan negara-negara emiten besar untuk membayar biaya kerusakan iklim akibat emisi yang mereka hasilkan selama ini. Bahkan draf kesepakatan COP27 hanya memuat rumusa dana kerugian dan kerusakan iklmi (loss and damage fund) tanpa menjelaskan secara detil apa akar soalnya.
Hal itu bisa kita amati misalnya melalu kritikan yang disampaikan oleh pegiat lingkungan yang tergabung dalam Green Peace yang menggelar aksi dalam forum G20 di Bali. Pesan utama yang merak sampaikan yakni bahwa Indonesia justru tidak konsisten menerapkan transisi energi sebab dalam Rencana Umum Pengadaan Tenaga Listrik (RUPTL), Indonesia masih akan menggunakan batu bara, pararel dengan phase out secara bertahap hingga tahun 2056. Bagian paling ironis dari itu adalah bahwa mayoritas negara G20 merupakan penyumbang emisi terbesar yakni hampir 80 persen dari emisi global.
Bagian paling lucu dari semuanya itu disampaikan oleh Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak, Senin (21/11) bahwa ini menandakan keengganan negara-negara emiten besar untuk membayar biaya kerusakan iklim akibat emisi yang mereka hasilkan selama ini. Bahkan draf kesepakatan COP27 hanya memuat rumusa dana kerugian dan kerusakan iklmi (loss and damage fund) tanpa menjelaskan secara detil apa akar soalnya.
Kepala Delegasi COP27 Greennpeace International Yeb Sano bahkan menilai bahwa draf tersebut mencerminkan perundingan yang berjalan dengan buntu. “Draf kesepakatan itu melepaskan tanggung jawab untuk menangkap urgensi yang diungkapkan oleh banyak negara tentang perlunya menghapus bahan bakar fosil. Penyangkalan ini harus segera diakhiri dengan menutup energi fosil,” katanya. (lihat gambar nomor 4).
Kedua, COP27 disponsori oleh Coca-Cola, produser dan pencemar plastik terbesar dunia. Bagian ini paling penting dalam rangka menjadikan keadilan iklim sebagai bagian penting dari sebuah upaya mendesiminasi gagasan keberlanjutan lingkungan bagi semua generasi, terutama generasi muda yang cerdas dan masih berumur panjang.
Ketiga, puluhan orang yang mau lakukan aksi protes ditahan aparat di Mesir. Bahkan terjadinya pembatasan hak masyarakat sipil untuk hadir secara sistematis. Bahkan Gretta Thunberg tidak hadir dalam event itu dengan alasan bahwa COP27 sebagai pertemuan pencucian uang, bukan sungguh-sungguh untuk mengubah semua sistem. Ia mengatakan demikian, “I’m not going to COP27 for many reasons, but the space for civil society this year is extremely limited”.
Keempat, angka 27 pada COP27 artinya sudah 27 kali pertemuan ini digelar namun situasinya memburuk. Lalu, kita disuruh percaya pada para ‘pemimpin’ jenis ini?
Kelima, Pengabaian terhadap industri militer. Bagian penting lain yang luput dari agenda bahasan COP27 yakni industri militer dan konflik bersenjata.
Kelima, Pengabaian terhadap industri militer. Bagian penting lain yang luput dari agenda bahasan COP27 yakni industri militer dan konflik bersenjata.
Berdasarkan data dari Departemen Pertahanan, instalasi militer domestik dan luar negeri menyumbnag sekitar 40 persen dari emisi gas rumah kaca. Ada 800 pangkalan militer AS di 90 negara dan wilayah di seluruh dunia. Pangkalan sebesar sebuah kota yang dilengkapi dengan segala sesuatu yang membutuhkan energi mulai dari instalasi senjata nuklir, sekolah dan pusat perbelanjaan, lapangan terbang, pelabuhan, dan lain-lain. Yang menanggung beban perubahan iklim justru adalah penduduk asli, orang miskin dan Dunia Selatan (Global South). Ini belum termasuk konflik bersenjata yang sengaja didesain oleh politik luar negeri sejak Global War on Terror paska robohnya WTC diikuti invansi ke Timur Tengah.
Khusus untuk Indonesia, negara ini masih punya pekerjaan rumah memenuhi target program minimum essential force (MEF) yang dimulai pada 2010 lalu. MEF adalah program pemenuhan standar kekuatan minimum TNI untuk menghadapi ancaman perang. Untuk menyukseskan program tersebut, pemerintah terus meningkatkan anggaran Kementerian Pertahanan. Angka anggaran tersebut dalam lima tahun ke belakang bisa dilihat dalam grafik di bawah ini.
Khusus untuk Indonesia, negara ini masih punya pekerjaan rumah memenuhi target program minimum essential force (MEF) yang dimulai pada 2010 lalu. MEF adalah program pemenuhan standar kekuatan minimum TNI untuk menghadapi ancaman perang. Untuk menyukseskan program tersebut, pemerintah terus meningkatkan anggaran Kementerian Pertahanan. Angka anggaran tersebut dalam lima tahun ke belakang bisa dilihat dalam grafik di bawah ini.
 |
| Sumber Gambar: Jurno.id |
Lalu mengapa bagian ini penting dibahas?
Sekretaris Departemen Pertahanan AS, Joe Bryan misalnya mengatakan, “But I want to stress that….climate change does not alter the Army’s overall mission, which is to deploy, fight, and win” (TIME, 17 Februari 2022). Padahal, sebelumnya, administrasi Biden memotong anggaran pemerintahan federal yang menunjukan bahwa penggunaan energi untuk industri pertahanan AS antara 77 % dan 80% selama dua dekade terakhir. Jika Pentagon adalah sebuah negara, maka lembaga itu menjadi penghasil karbon dioksida terbesar ke-55 di dunia.
Sekretaris Departemen Pertahanan AS, Joe Bryan misalnya mengatakan, “But I want to stress that….climate change does not alter the Army’s overall mission, which is to deploy, fight, and win” (TIME, 17 Februari 2022). Padahal, sebelumnya, administrasi Biden memotong anggaran pemerintahan federal yang menunjukan bahwa penggunaan energi untuk industri pertahanan AS antara 77 % dan 80% selama dua dekade terakhir. Jika Pentagon adalah sebuah negara, maka lembaga itu menjadi penghasil karbon dioksida terbesar ke-55 di dunia.
Mengapa bisa begitu? Jawabannya: karena perspektif perang adalah perspekif dominan yang mengontrol politik dan ekonomi. Menhan Prabowo mengatakan, “Perang memang tidak populer. Tetapi ini kuncinya. Bangsa-bangsa dan negara yang tidak siap perang, nasibnya selalu dijajah orang lain. Ini pelajaran sejarah.
Perspektif ini juga sama dengan apa yang dikatakan oleh Departemen Perminyakan dan Air Angkatan Darat AS, Fort Lee, “Bahan Bakar adalah darah militer dan sangat penting bagi hidupnya operasi”.
Skenario Perubahan yang Bisa Dilakukan
Nah, setelah memahami dinamika di atas, bagian ini menjadi sajian penutup sekaligus kerangka pemikiran terkait skenario seperti apa yang perlu kita pikirkan dalam rangka memajukan keberlanjutan lingkungan baik secara personal maupun secara kolektif.
Skenario Perubahan yang Bisa Dilakukan
Nah, setelah memahami dinamika di atas, bagian ini menjadi sajian penutup sekaligus kerangka pemikiran terkait skenario seperti apa yang perlu kita pikirkan dalam rangka memajukan keberlanjutan lingkungan baik secara personal maupun secara kolektif.
Disebut demikian karena keadilan iklim merupakan konsep yang digunakan secara berbeda sesuai dengan konteks tertentu, tetapi keadilan lingkungan datang pertama kali dan berakar dari pengalaman marginalisasi komunitas kulit hitam yang melawan balik untuk mempertahankan lingkungan mereka yang digunakan sebagai lokasi pembuangan limbah beracun.
Artinya, keadilan iklim merupakan istilah baru yang berkaitan dengan ketidakadilan yang spesifik yang kemudian mempercepat krisis iklim, tetapi juga dihubungkan dengan gerakan sosial tertentu pada abad ke-21 sehingga menjadikan istilah itu menjadi isu yang mendapat atau menarik perharian solidaritas internasional (Rebellion Global, 22 Maret 2022).
Oleh sebab itu, butuh kampanye berkelanjutan yang memastikan gagasan seperti ini tetap berkembang dan ditanamkan dalam diri peserta didik terutama generasi muda yang masih ingin menaruh perhatian serius terhadap masa depan lingkungan.
Dalam rangka menjawabi urgensitas keadilan iklim (climate justice) di atas, penting untuk dijabarkan apa itu keadilan. Keadilan tidak sama dengan kesetaraan. Jika kesetaraan bisa diilustrasikan dengan memberikan roti dalam bentuk dan ukuran yang sama kepada sekaligus orang dewasa dan anak-anak maka keadilan adalah memberikan roti sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Artinya, berdasarkan kebutuhan dan haknya, anak-anak pasti tidak mampu menghabiskan roti dalam ukuran yang sama dengan yang kita berikan kepada orang dewasa.
Dengan kata lain, ketika bicara tentang keadian iklim, kita mesti fokus pada sumber pemicu pemanasan global, yakni produksi emisi. Mitigasi krisis iklim, dengan nama karbon netral atau skema apa pun untuk menurunkan emisi, pertama-tama harus menargetkan produsennya.
Jika sumber utama gas rumah kaca dari energi fosil, maka konsep keadilan iklim adalah menyetop pemakaian energi fosil dengan menggantinya dengan energi terbarukan. Jika emisi gas rumah kaca akibat kebakaran hutan dan deforestasi, keadilan iklim mendorong mitigasi melalui penegakan manajemen hutan yang lestari.
Konsep keadilan iklim menyasar problem utama pemanasan global saat ini: produksi emisi yang tak terkendali untuk menggapai peradaban dan kemajuan manusia. Disebut demikian karena “kKrisis iklim,” kata Friederike Otto, 10 Tokoh Pilihan Majalah Nature 2021, “merupakan satu faktor paling besar pendorong ketidakadilan”.
Oleh sebab itu, butuh kampanye berkelanjutan yang memastikan gagasan seperti ini tetap berkembang dan ditanamkan dalam diri peserta didik terutama generasi muda yang masih ingin menaruh perhatian serius terhadap masa depan lingkungan.
Dalam rangka menjawabi urgensitas keadilan iklim (climate justice) di atas, penting untuk dijabarkan apa itu keadilan. Keadilan tidak sama dengan kesetaraan. Jika kesetaraan bisa diilustrasikan dengan memberikan roti dalam bentuk dan ukuran yang sama kepada sekaligus orang dewasa dan anak-anak maka keadilan adalah memberikan roti sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Artinya, berdasarkan kebutuhan dan haknya, anak-anak pasti tidak mampu menghabiskan roti dalam ukuran yang sama dengan yang kita berikan kepada orang dewasa.
Dengan kata lain, ketika bicara tentang keadian iklim, kita mesti fokus pada sumber pemicu pemanasan global, yakni produksi emisi. Mitigasi krisis iklim, dengan nama karbon netral atau skema apa pun untuk menurunkan emisi, pertama-tama harus menargetkan produsennya.
Jika sumber utama gas rumah kaca dari energi fosil, maka konsep keadilan iklim adalah menyetop pemakaian energi fosil dengan menggantinya dengan energi terbarukan. Jika emisi gas rumah kaca akibat kebakaran hutan dan deforestasi, keadilan iklim mendorong mitigasi melalui penegakan manajemen hutan yang lestari.
Konsep keadilan iklim menyasar problem utama pemanasan global saat ini: produksi emisi yang tak terkendali untuk menggapai peradaban dan kemajuan manusia. Disebut demikian karena “kKrisis iklim,” kata Friederike Otto, 10 Tokoh Pilihan Majalah Nature 2021, “merupakan satu faktor paling besar pendorong ketidakadilan”.









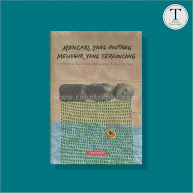
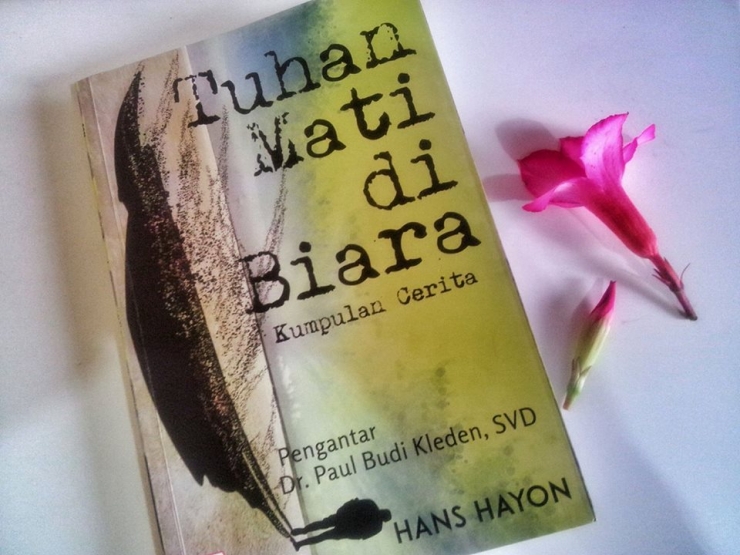

Post a Comment
Post a Comment