Artikel ini dibuka dengan beberapa klarifikasi yang penting untuk dikemukakan. Disebut demikian karena sudah terlalu banyak salah kaprah yang kita lakukan ketika berpikir dan berbicara tentang adat dan masyarakat adat di Indonesia.
Akar Soal
Lalu mengapa kecenderungan seperti ini semakin menguat pada abad ini?
Jawaban pertama, intervensi sistem ekonomi neoliberal yang menjadikan sistem produksi sebagai panglima. Artinya, jika ada unsur yang dianggap tidak produktif, dapat dengan mudah dieliminasi dan dibuat kabur basis perlawanannya. Proses pengaburan masyarakat adat sebagai basis material perlawanan ini berlangsung juga di segmen lain misalnya kaum muda dan kaum buruh. Mengapa demikian? Ya, karena kategori tersebut merupakan basis munculnya protes.
Kedua, masih berhubungan dengan poin pertama, penguatan kecenderungan itu semakin menjadi-jadi di negara yang memiliki sejarah basis perlawanan yang terbatas. Gerakan petani (marhaen) dan PKI misalnya merupakan dua contoh yang patut disebut di sini sebelum akhirnya bubar ketika Presiden Soekarno dilengserkan.
Selanjutnya, dengan naiknya Presiden Soeharto ke tampuk kepemimpinan, basis perlawanan masyarakat (termasuk masyarakat adat) perlahan dilemahkan dan ditranformasi ke dalam apa yang hari ini kita kenal sebagai Taman Mini Indonesia, ritus dan protokol kebudayaan, serta artefak dan teks-teks mata pelajaran. Itulah miniatur mainan Orde Baru yang merekayasa basis perlawanan kultural menjadi sekadar tontotan dan soal ujian. Dan sejak saat itu, hingga kini, masyarakat adat menjelma destinasi wisata, dipromosikan, dipajang, dan diperjualbelikan dalam bisnis tourisme.
Memanggil Kembali yang Hilang
Padahal, eksistensi masyarakat adat tidak seperti itu. Ada begitu banyak dimensi yang sangat kaya dan berguna sekaligus dapat menjadi acuan bagi peradaban masyarakat hari ini. Sebuah jenis peradaban yang mengalami anonimitas: enggan meninggalkan masa lalunya namun gagap menyesuaikan diri dengan perubahan yang akan datang.
Selain di bidang kesehatan, masyarakat adat juga memiliki sistem daya dukung sosial dan ekonomi tersendiri di luar dari parameter pembangunan yang dipahami oleh negara.
Contoh-contoh di atas merupakan eksemplar yang sangat penting untuk dibahas bukan hanya dalam perspektif medis seperti yang cenderung masif di negara ini, melainkan dari perspektif politik. Artinya, kemampuan masyarakat adat dalam mendesain dan merumuskan sistem kesehatannya sendiri hendaknya menjadi salah satu pemantik bagi keberlanjutan perjuangan mereka di bidang lain seperti ekonomi, religiositas, pemerintahan, dan pandangan hidup. Hal ini mendesak dilakukan agar eksistensi masyarakat adat tidak lagi diintervensi oleh logika pembangunan yang cenderung masif akhir-akhir ini.
Apa yang Harus Dilakukan?
Pertama, dalam konteks umum, ubahlah perspektif yang memandang masyarakat adat sekadar atribut pelengkap dalam protokol kenegaraan dan industri tourisme. Hal ini penting agar menghindarkan kita dari kecenderungan memahami kebudayaan, adat dan masyarakat adat secara artifisial semata.
Kedua, masukkan masyarakat adat ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Bagian ini penting dalam rangka mendesiminasi gagasan terkini terkait masyarakat adat kepada peserta didik sejak dini. Selain itu, pemahaman tersebut juga akan berkelanjutan dan kontekstual karena memberikan makna bagi apa yang sudah dilihat dan dihidupi oleh peserta didik di lingkungan di mana ia tinggal.
Ketiga, perkuat kapasitas negosiasi di level parlemen. Jujur, tanpa ada agensi politik di parlemen, perjuangan dan negosiasi kita terhambat secara serius. Oleh sebab itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang advokasi masyarakat adat perlu memiliki wakil di parlemen agar apa yang disuarakan dapat tersampaikan ke corong pemerintah daerah dan nasional.
Keempat, perkuat relasi aktivis masyarakat adat antarnegara. Bagian ini menjadi penting persis ketika tidak ada keterakaitan antara para aktivis masyarakat adat dan aktivis isu-isu lain. Masing-masing mereka tampak berjalan sendiri-sendiri.
Kelima, perlunya sinergitas antarisu dan kolaborasi antarlembaga.
Kekeliruan Pertama berasal dari kecenderungan kita mengerti adat dan masyarakat adat terbatas pada busana, tarian, dan makanan lokal. Padahal kalau mau jujur, kita bahkan tidak terlalu peduli apa makna di balik semuanya itu.
Kekeliruan Kedua masih berhubungan dengan yang pertama yakni kecenderungan memahami masyarakat adat terbatas pada tanah. Terlepas dari tanah telah menjadi komoditas penting dalam abad ini, cara kita memahami tanah sudah benar-benar terlepas dari hubungannya dengan masyarakat di mana tanah itu berada. Anda bisa amati gejala ini persis di dalam kampus di mana tidak sedikit mahasiwa arsitektur misalnya tidak terlalu peduli jika bangunan yang ia desain itu akan didirikan di atas lahan sengketa.
Kekeliruan Ketiga tampak dalam kecenderungan kita memahami masyarakat adat berdasarkan atribut budaya yang fragmentaris, terpisah-pisah. Akibatnya, kita gagap merumuskan hubungan atau relasi antara dimensi sosial politik dari tanah, makanan, dan busana.
Kekeliruan Keempat justru jauh lebih penting dari itu yakni kita lupa bahwa dimensi paling berharga dari masyarakat adat adalah manusia. Artinya jelas, tanpa masyarakat adat mustahil ada bahasa daerah, makanan lokal, busana adat, dan tanah adat. Artinya, fokus utama kita ketika berbicara tentang masyarakat adat mestinya adalah manusia — bukan hal yang lain!
Kekeliruan Kedua masih berhubungan dengan yang pertama yakni kecenderungan memahami masyarakat adat terbatas pada tanah. Terlepas dari tanah telah menjadi komoditas penting dalam abad ini, cara kita memahami tanah sudah benar-benar terlepas dari hubungannya dengan masyarakat di mana tanah itu berada. Anda bisa amati gejala ini persis di dalam kampus di mana tidak sedikit mahasiwa arsitektur misalnya tidak terlalu peduli jika bangunan yang ia desain itu akan didirikan di atas lahan sengketa.
Kekeliruan Ketiga tampak dalam kecenderungan kita memahami masyarakat adat berdasarkan atribut budaya yang fragmentaris, terpisah-pisah. Akibatnya, kita gagap merumuskan hubungan atau relasi antara dimensi sosial politik dari tanah, makanan, dan busana.
Kekeliruan Keempat justru jauh lebih penting dari itu yakni kita lupa bahwa dimensi paling berharga dari masyarakat adat adalah manusia. Artinya jelas, tanpa masyarakat adat mustahil ada bahasa daerah, makanan lokal, busana adat, dan tanah adat. Artinya, fokus utama kita ketika berbicara tentang masyarakat adat mestinya adalah manusia — bukan hal yang lain!
Akar Soal
Lalu mengapa kecenderungan seperti ini semakin menguat pada abad ini?
Jawaban pertama, intervensi sistem ekonomi neoliberal yang menjadikan sistem produksi sebagai panglima. Artinya, jika ada unsur yang dianggap tidak produktif, dapat dengan mudah dieliminasi dan dibuat kabur basis perlawanannya. Proses pengaburan masyarakat adat sebagai basis material perlawanan ini berlangsung juga di segmen lain misalnya kaum muda dan kaum buruh. Mengapa demikian? Ya, karena kategori tersebut merupakan basis munculnya protes.
Kedua, masih berhubungan dengan poin pertama, penguatan kecenderungan itu semakin menjadi-jadi di negara yang memiliki sejarah basis perlawanan yang terbatas. Gerakan petani (marhaen) dan PKI misalnya merupakan dua contoh yang patut disebut di sini sebelum akhirnya bubar ketika Presiden Soekarno dilengserkan.
Selanjutnya, dengan naiknya Presiden Soeharto ke tampuk kepemimpinan, basis perlawanan masyarakat (termasuk masyarakat adat) perlahan dilemahkan dan ditranformasi ke dalam apa yang hari ini kita kenal sebagai Taman Mini Indonesia, ritus dan protokol kebudayaan, serta artefak dan teks-teks mata pelajaran. Itulah miniatur mainan Orde Baru yang merekayasa basis perlawanan kultural menjadi sekadar tontotan dan soal ujian. Dan sejak saat itu, hingga kini, masyarakat adat menjelma destinasi wisata, dipromosikan, dipajang, dan diperjualbelikan dalam bisnis tourisme.
Memanggil Kembali yang Hilang
Padahal, eksistensi masyarakat adat tidak seperti itu. Ada begitu banyak dimensi yang sangat kaya dan berguna sekaligus dapat menjadi acuan bagi peradaban masyarakat hari ini. Sebuah jenis peradaban yang mengalami anonimitas: enggan meninggalkan masa lalunya namun gagap menyesuaikan diri dengan perubahan yang akan datang.
Terdapat begitu banyak contoh yang dapat dijadikan landasan bagi argumentasi artikel ini. Salah satunya yakni pandemi covid-19. Terlepas dari perspektif yang mengatakan bahwa pandemi mengungkapkan secara jelas bahwa sedang terjadi krisis neoliberalisme, masyarakat adat merupakan satu-satunya komunitas yang mampu bertahan dalam situasi tersebut. Masyarakat adat Mentawai (BBCNewsIndonesia, 13 November 2021), Suku Baduy di Banten, Orang Rimba di Bukit Dua Belas-Jambi, dan masyarakat adat Boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT (Kemdikbud.go.id, 21 Februari 2022) adalah beberapa dari sekian banyak contoh lain yang perlu dicatat di sini.
Argumen di atas tidak mengada-ada. Dalam salah satu chapter berjudul Minding the Mind, Emeran Mayer dan Clifford B. Saper menulis kalimat pembuka artikel mereka dengan pernyataan yang cukup mengejutkan.
Argumen di atas tidak mengada-ada. Dalam salah satu chapter berjudul Minding the Mind, Emeran Mayer dan Clifford B. Saper menulis kalimat pembuka artikel mereka dengan pernyataan yang cukup mengejutkan.
Selama beberapa abad dalam setiap masyarakat, sebelum obat-obatan dan pusat kesehatan didirikan, proses penyembuhan penyakit dilakukan dengan berdasarkan pada sistem psikologi indigenous yang berpusat pada otak. Konsep universal tentang praktik penyembuhan tradisional mengikuti kepercayaan terhadap: Pertama, kepercayaan pada kekuatan universal (jiwa, chi, prana, daya tarik bidatang dan alam). Kedua, kepercayaan pada persatuan antara pikiran, tubuh, dan lingkungan. Ketiga, konsep tentang kesehatan sebagai kondisi harmoni antara pikiran dan tubuh, dan antara organisme dan alam. Konsep tentang penyakit sebagai hilangnya harmoni (Mayer and Saper, 2000: 3).Dalam konteks masyarakat adat di Indonesia, diantaranya Suku Baduy, keputusan masyarakat untuk mengantisippasi covid-19 dilakukan dengan cara mengkarantina wilayah mereka sesuai dengan pedoman hidup atau pikukuh. Pedoman itu menekankan bahwa rusaknya lingkungan, kacaunya ekosistem dan rantai makanan merupakan akar dari munculnya wabah penyakit seperti covid-19 (bandingkan etimologi kata kosmetik yang berasal dari kata Bahasa Latin cosmos yang berarti keteraturan atau keharmonisan). Oleh sebab itu, penyembuh (katakanlah, dukun), dilihat sebagai katalisator yang menggunakan intervensi untuk memengaruhi kemampuan tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dengan tujuan memperbaiki harmoni yang telah rusak tadi (Mayer and Saper, 2000: 3).
Hal yang sama juga berlaku dalam masyarakat adat Punan Tubu di Kalimantan yang mengenal wabah sebagai kelapit yang dicirikan dengan orang sehat hari ini, lalu sakit dan besok bisa mati. Demikian juga masyarakat adat Topo Uma di Sulawesi Tengah yang memiliki pengetahuan lokal tentang penyakit menular yang terintgrasi dalam pola ruang dan perkampungan (Kemdikbud.go.id, 21 Februari 2022).
 |
| Ilustrasi Hikayat Masyarakat Adat & Pandemi. (Project M/Garisinau di bawah lisensi Creative Commons BY-NC-ND 2.0) |
“Saya ingin menangis. Sekarang semua serba uang, untuk biaya kuliah Lepon saja Rp5 juta sampai Rp6 jutaan tiap semester,” kata Aman Lepon (47), salah seorang warga Mentawai (BBCNewsIndonesia, 13 November 2021).
Dengan kata lain, pernyataan itu secara tegas mengoreksi perspektif umum yang mengukur segala sesuatu dari parameter uang. Akibatnya, tidak heran jika ada sebagian masyarakat adat lain yang menolak keras segala bentuk intervensi negara melalui bantuan langsung tunai (BLT), dan berbagai jenis bantuan lain karena dianggap “menghina” kemampuan berdikari masyarakat adat.
Tidak perlu dibantu, negara tidak perlu pusing dengan desa Boti!Kalimat itu diucapkan oleh Balsasar O. I Benu, salah seorang tokoh masyarakat adat Boti di TTS, NTT ketika menjadi narasumber dalam talk show Ketahanan Masyarakat Boti di Tengah Bencana Pandemi Covid-19, 20 Agustus 2020 lalu (Projectmultatuli.org, 24 Juni 2021).
Contoh-contoh di atas merupakan eksemplar yang sangat penting untuk dibahas bukan hanya dalam perspektif medis seperti yang cenderung masif di negara ini, melainkan dari perspektif politik. Artinya, kemampuan masyarakat adat dalam mendesain dan merumuskan sistem kesehatannya sendiri hendaknya menjadi salah satu pemantik bagi keberlanjutan perjuangan mereka di bidang lain seperti ekonomi, religiositas, pemerintahan, dan pandangan hidup. Hal ini mendesak dilakukan agar eksistensi masyarakat adat tidak lagi diintervensi oleh logika pembangunan yang cenderung masif akhir-akhir ini.
Apa yang Harus Dilakukan?
Pertama, dalam konteks umum, ubahlah perspektif yang memandang masyarakat adat sekadar atribut pelengkap dalam protokol kenegaraan dan industri tourisme. Hal ini penting agar menghindarkan kita dari kecenderungan memahami kebudayaan, adat dan masyarakat adat secara artifisial semata.
Kedua, masukkan masyarakat adat ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Bagian ini penting dalam rangka mendesiminasi gagasan terkini terkait masyarakat adat kepada peserta didik sejak dini. Selain itu, pemahaman tersebut juga akan berkelanjutan dan kontekstual karena memberikan makna bagi apa yang sudah dilihat dan dihidupi oleh peserta didik di lingkungan di mana ia tinggal.
Ketiga, perkuat kapasitas negosiasi di level parlemen. Jujur, tanpa ada agensi politik di parlemen, perjuangan dan negosiasi kita terhambat secara serius. Oleh sebab itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang advokasi masyarakat adat perlu memiliki wakil di parlemen agar apa yang disuarakan dapat tersampaikan ke corong pemerintah daerah dan nasional.
Keempat, perkuat relasi aktivis masyarakat adat antarnegara. Bagian ini menjadi penting persis ketika tidak ada keterakaitan antara para aktivis masyarakat adat dan aktivis isu-isu lain. Masing-masing mereka tampak berjalan sendiri-sendiri.
Kelima, perlunya sinergitas antarisu dan kolaborasi antarlembaga.
Masih berkaitan dengan poin ke-empat, perlu juga ada keterkaitan isu di mana isu masyarakat adat dihubungkan dengan isu lain seperti perubahan iklim, revolusi di bidang kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Sementara itu, kolaborasi antarlembaga dibangun dengan cara menghubungkan lembaga yang bergerak di bidang masyarakat adat dengan lembaga negara dan non-state lainnya.
Ada dua cara yang dapat kita pakai untuk mewujudkan poin keempat dan kelima di atas yakni melalui pendekatan isu atau pendekatan aktor dan kelembagaan. Hanya dengan cara itu, upaya terkini terkait RUU Masyarakat Adat dapat disahkan.




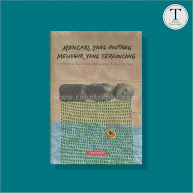
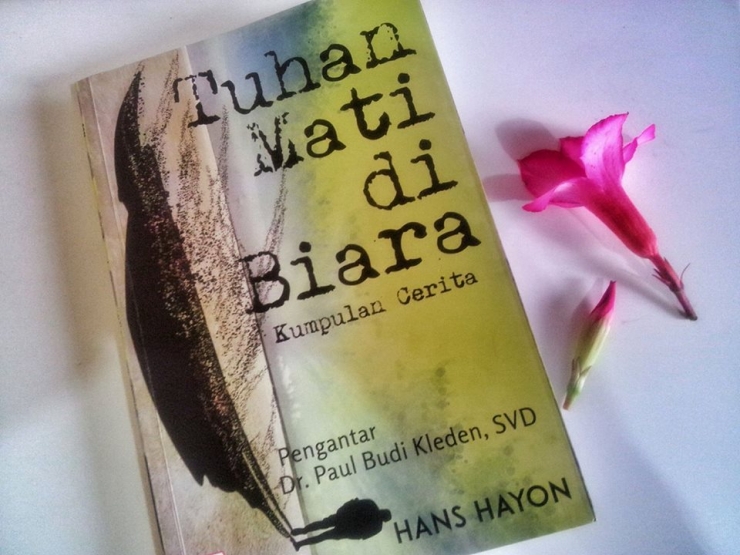

Post a Comment
Post a Comment