Saya belum terbiasa meneguk secangkir kopi. Alasan yang melatarbelakangi keengganan tersebut justru karena efek gagal kantuk yang dihasilkan oleh kandungan zat kaffein dalam kopi. Bahkan menurut kesaksian beberapa orang kawan yang begitu maniak kopi, selain membuat sulit tidur, juga menimbulkan gangguan pada jantung.
Oleh sebab itu, saya memutuskan untuk sama sekali tidak meminum kopi mulai saat ini. Satu-satunya teman karib saya ketika sedang membaca hanyalah secangkir teh manis. Ditemani sebungkus rokok, tentunya.
Sulit bagi saya untuk menjelaskan apa hubungan antara meningkatnya kreativitas kerja saraf-saraf dalam otak dengan mengisap sebatang rokok. Entahlah, sensasi seperti itu terkesan sangat remeh namun pada hampir setiap detik selalu memberikan saya alasan untuk terus membaca, berpikir, dan menulis hingga saat ini.
Kebiasaan saya untuk tidak mengopi terpaksa gagal setelah beberapa hari menetap di tempat ini: Colol, Manggarai.
Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan oleh universitas tempat saya kuliah, Colol merupakan lokasi yang tampan untuk menjalani Kuliah Kerja Nyata. Begitu ramahnya perangai keluarga yang menjemput kedatangan saya cukup untuk menghilangkan rasa penat selepas jauhnya perjalanan ke tempat ini.
Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan oleh universitas tempat saya kuliah, Colol merupakan lokasi yang tampan untuk menjalani Kuliah Kerja Nyata. Begitu ramahnya perangai keluarga yang menjemput kedatangan saya cukup untuk menghilangkan rasa penat selepas jauhnya perjalanan ke tempat ini.
Hari masih sore ketika bersama semua anggota keluarga, kami duduk bersimpuh di teras rumah. Dan di antara riuhnya percakapan yang dibangun, mendadak muncul seorang gadis menyuguhkan kami masing-masing secangkir kopi.
Belum sempat saya tolak, gadis itu telah lebih dahulu meleparkan senyum. Senyum yang membuat saya terpaksa membatalkan niat untuk berdosa karena menolak secangkir kopi yang ia suguhkan dari hati yang paling tulus. Dan sejak itu pula saya tahu bahwa keluarga ini memiliki seorang puteri.
“Nu, mulai hari ini, nana menginap di rumah kita. Ayo, silahkan berkenalan,” desis sang Ayah.
“Saya Sisilia,” ujar gadis itu sambil meletakkan sepiring pisang goreng yang membuat saya merasa kaget bercampur malu karena diketahui sedang memperhatikan perangainya dengan tatapan paling lama.
________________
“Saya Sisilia,” ujar gadis itu sambil meletakkan sepiring pisang goreng yang membuat saya merasa kaget bercampur malu karena diketahui sedang memperhatikan perangainya dengan tatapan paling lama.
Belum sempat memperkenalkan diri kepadanya, Sisilia buru-buru kembali ke dapur.
“Kami memiliki seorang puteri. Namanya Sisilia.” Ayah angkat saya mulai membuka pembicaraan.
“Apakah dia tidak mengenyam pendidikan. Seperti, kuliah, begitu?”
Saya tahu ini bukan pertanyaan yang pantas, namun karena alasan apa, saat ini saya sedang kehabisan ide untuk berbicara.
“Tidak nak,” sambung ibu dengan raut wajah memerah.
Dan kami terdiam.
Terdengar suara ribut-ribut dari arah dapur. Gelas itu pecah berkeping setelah membentur lantai. Dan saya tahu jika Sisilia tidak ingin masa lalunya kembali diungkit. Apalagi diceritakan kepada orang asing seperti saya.
“Kami memiliki seorang puteri. Namanya Sisilia.” Ayah angkat saya mulai membuka pembicaraan.
“Apakah dia tidak mengenyam pendidikan. Seperti, kuliah, begitu?”
Saya tahu ini bukan pertanyaan yang pantas, namun karena alasan apa, saat ini saya sedang kehabisan ide untuk berbicara.
“Tidak nak,” sambung ibu dengan raut wajah memerah.
Dan kami terdiam.
Terdengar suara ribut-ribut dari arah dapur. Gelas itu pecah berkeping setelah membentur lantai. Dan saya tahu jika Sisilia tidak ingin masa lalunya kembali diungkit. Apalagi diceritakan kepada orang asing seperti saya.
***
Begitu tiba, wangi kembang tanaman kopi mendadak mengerubungi hidung saya. Tanaman itu tampak begitu terawat. Di bawah batangnya yang kokoh, terdapat gumpalan tanah yang baru saja digembur. Karena ditanam dengan jarak yang cukup rapat, berada di bawah naungan rimbun daun kopi membuat keadaan tampak agak gelap.
Seperti ada masa lalu yang tertinggal pada ranting-rantingnya. Meminta saya sekedar untuk mengelus pinggang batangnya yang letih menampung rindu. Dan saya yakin bahwa selama ini orang belum cukup peduli pada kecamuk rindu akar-akar tanaman itu ketika mereka dengan santai menyeruput secangkir kopi menjelang petang. Rindu pada siapa? Mungkin air. Mungkin rahasia.
Saya benar-benar tidak tahu.
“Perkebunan ini merupakan hasil kerja keras dari Rustam.” gadis itu bergumam pelan sambil melamunkan sesuatu.
“Siapakah dia, Rustam itu?” tanya saya penasaran.
“Calon suami saya. Ia meninggal di tempat ini dengan cara menggantung tubuhnya…” Sisilia seperti tak kuasa melanjutkan kalimatnya. Ranting kopi yang kerdil di ujung sana bagai tersangkut dalam tenggorokkannya yang uzur.
“Maaf. Bukan maksud saya untuk menguarkan masa lalu keluargamu.”
Jujur, saya merasa sangat bersalah. Dan sangat kaget. Namun seperti membaca pikiran saya, gadis itu melanjutkan,
“Tak apalah. Namanya juga manusia. Ia hanya mampu bertahan hidup karena memiliki masa lalu.” Lanjutnya, “O ya. Rustam bunuh diri di tempat ini. Begitulah. Ia menggantung tubuhnya dengan seutas tali pada dahan salah satu pohon kopi. Alasannya sederhana saja: ia tak mau perkebunan ini dihibahkan kepada pemerintah kabupaten.”
“Perkebunan ini merupakan hasil kerja keras dari Rustam.” gadis itu bergumam pelan sambil melamunkan sesuatu.
“Siapakah dia, Rustam itu?” tanya saya penasaran.
“Calon suami saya. Ia meninggal di tempat ini dengan cara menggantung tubuhnya…” Sisilia seperti tak kuasa melanjutkan kalimatnya. Ranting kopi yang kerdil di ujung sana bagai tersangkut dalam tenggorokkannya yang uzur.
“Maaf. Bukan maksud saya untuk menguarkan masa lalu keluargamu.”
Jujur, saya merasa sangat bersalah. Dan sangat kaget. Namun seperti membaca pikiran saya, gadis itu melanjutkan,
“Tak apalah. Namanya juga manusia. Ia hanya mampu bertahan hidup karena memiliki masa lalu.” Lanjutnya, “O ya. Rustam bunuh diri di tempat ini. Begitulah. Ia menggantung tubuhnya dengan seutas tali pada dahan salah satu pohon kopi. Alasannya sederhana saja: ia tak mau perkebunan ini dihibahkan kepada pemerintah kabupaten.”
_____________
Sampai pada titik ini, barulah saya sadar. Pernah, sebulan yang lalu, saya membaca sebuah artikel pada Jurnal Ledalero-Maumere-Flores-NTT. Tulisan itu mengupas persoalan pembabatan perkebunan kopi oleh pemerintah kabupaten dengan dalil konservasi.
Bukankah hal ini merupakan pernyataan yang kontradiktif? Dalam hati, saya tak sanggup membayangkan betapa berkecamuknya perasaan Sisilia. Peristiwa kematian yang menimpa keluarganya terlampau pahit untuk disebut sebagai cobaan.
“Kenapa kamu terdiam?” tanya Sisilia sambil menepuk bahu saya.
“Di sini udaranya segar.” Ujar saya mengalihkan topik pembicaraan.
“Ya. Mungkin karena itulah, berjam-jam lamanya saya dan Rustam biasa menghabiskan waktu di sini.”
“O ya?” Wajah saya kembali memerah.
“Rustam itu memang agak aneh. Katanya, di tempat ini kenangan seperti dibangkitkan dan masa depan dimungkinkan.”
Mendengar kalimat ini, saya menjadi bingung dan tampak begitu bodoh.
“Kau lihat pohon itu?” ujar Sisilia dengan nada yang tak sempat menjadi kalimat tanya. Jari telunjuknya mengarah ke sebuah pohon di ujung kebun. “Pohon itu ditanam ketika dilangsungkannya acara pertunangan kami,” imbuhnya lirih.
“Sekali lagi saya mohon maaf karena kembali mengungkit masa lalumu.” Saya berujar demikian karena sudah tidak tahu harus mengatakan apa.
“Kesedihan saya pecah karena engkau tampak mirip dengannya. Terlebih saat hari pertama engkau tiba di rumah.”
Kali ini Sisilia berbicara sambil menatap saya dalam. Dan sekali lagi, saya tampak begitu bodoh.
“Ayo, kita jalan-jalan.”
Sebelum sempat menjawab ajakannya, Sisilia mengapit lengannya persis di bahu saya. Walaupun hari hampir malam namun tidak saya pedulikan. Kami berjalan menyusuri satu per satu pohon kopi. Menjamah ranting-rantingnya yang mulai basah. Dahan pohon itu seakan bergoyang menyambut kedatangan kami sebagai sepasang mungkin. Sesampainya di pinggir kebun, dekat hutan, kegelapan mengelilingi tubuh saya. Mendekap mata saya.
“Kenapa kamu terdiam?” tanya Sisilia sambil menepuk bahu saya.
“Di sini udaranya segar.” Ujar saya mengalihkan topik pembicaraan.
“Ya. Mungkin karena itulah, berjam-jam lamanya saya dan Rustam biasa menghabiskan waktu di sini.”
“O ya?” Wajah saya kembali memerah.
“Rustam itu memang agak aneh. Katanya, di tempat ini kenangan seperti dibangkitkan dan masa depan dimungkinkan.”
Mendengar kalimat ini, saya menjadi bingung dan tampak begitu bodoh.
“Kau lihat pohon itu?” ujar Sisilia dengan nada yang tak sempat menjadi kalimat tanya. Jari telunjuknya mengarah ke sebuah pohon di ujung kebun. “Pohon itu ditanam ketika dilangsungkannya acara pertunangan kami,” imbuhnya lirih.
“Sekali lagi saya mohon maaf karena kembali mengungkit masa lalumu.” Saya berujar demikian karena sudah tidak tahu harus mengatakan apa.
“Kesedihan saya pecah karena engkau tampak mirip dengannya. Terlebih saat hari pertama engkau tiba di rumah.”
Kali ini Sisilia berbicara sambil menatap saya dalam. Dan sekali lagi, saya tampak begitu bodoh.
“Ayo, kita jalan-jalan.”
Sebelum sempat menjawab ajakannya, Sisilia mengapit lengannya persis di bahu saya. Walaupun hari hampir malam namun tidak saya pedulikan. Kami berjalan menyusuri satu per satu pohon kopi. Menjamah ranting-rantingnya yang mulai basah. Dahan pohon itu seakan bergoyang menyambut kedatangan kami sebagai sepasang mungkin. Sesampainya di pinggir kebun, dekat hutan, kegelapan mengelilingi tubuh saya. Mendekap mata saya.
Dan semuanya menjadi pekat.
Hitam.
_____________
Dari kejauhan, terdengar ribut suara orang memanggil nama saya. Beberapa menit kemudian, sebelum semuanya seperti lapang, seseorang berteriak tepat di samping saya.
“Sam ada di sini. Sudah kutemukan. Sam ada di sini. Sudah kutemukan.”
***
Kegiatan perkuliahan hari ini begitu membosankan. Masa praktek selama sebulan yang lalu telah menyedot hampir seluruh konsentrasi hidup saya. Di hadapan saya, rimbun daun kopi terhampar memadati lembar-lembar diktat kuliah. Akar-akarnya yang kekar tertanam di setiap halamannya. Sedangkan pada sisi kiri dan kanan, rantingnya menjulur lapang. Diseretnya keluar seperempat kumpulan huruf-huruf. Dan sebelum wangi kembang kopi kembali menusuk-nusuk hidung seperti waktu itu, cepat-cepat saya jauhkan diktat sialan itu. Beberapa mahasiswa melemparkan pandangan aneh.
_____________
“Kamu baik-baik saja, Sam?” Tanya salah seorang sahabat di samping saya. Tatapannya menyiratkan rasa cemas yang luar biasa.
“Iya. Tidak apa-apa.”
Seperti ada yang tidak beres dengan pikiran saya sendiri. Saya lalu memutuskan untuk kembali ke rumah sebelum kegiatan perkuliahan selesai. Dengan langkah gontai, saya berjalan ke luar ruangan. Pandangan seisi kelas mengiringi kepergian saya yang mendadak itu. Saya percaya, mereka sedang mencemaskan sesuatu walaupun saya sendiri tidak tahu persis apa itu.
Ketika sampai, tidak ada siapa-siapa di rumah. Mungkin Ayah dan Ibu masih di kantor dan sebentar lagi akan pulang. Dan dengan tergesa saya berjalan menuju dapur. Setelah menyiapkan secangkir kopi, saya putuskan untuk beristirahat sejenak di teras rumah. Sialnya, belum sempat menyeruput secangkir kopi, seorang wanita berlari kecil ke arah saya. Di tangannya, tergenggam sebuah amplop kuning gading. Dari jarak dekat, barulah saya tahu bahwa wanita yang mirip gadis itu adalah Ibu saya sendiri.
“Ada surat untukmu, Sam” ujar Ibu begitu tiba di hadapan saya. Perlahan tanpa dikomando, lengan saya seperti terangkat dan menyambut surat tersebut.
“Mungkin Ibu salah alamat.” Ujar saya setelah menatap amplop surat itu secara saksama. Jelas, tidak ada alamat yang mendetail tentang siapa pengirimnya. Hanya saja, di sudut kanan atas tertulis, untuk anakku Sam.
“Kata pegawai kantor Ibu, surat ini direkomendasikan oleh penulisnya sendiri. Bahkan penulis itu sendiri menjelaskan kepadanya perihal kepada siapa surat ini ditujukan,” timpal Ibu menirukan gaya pegawainya yang dari aksentuasi bicaranya sangat kental dengan dialek Manggarai.
____________
Tanpa berpikir panjang, surat itu saya buka. Lamat-lamat mata saya mengeja deretan kalimat yang tertera di atasnya.
“Sisilia telah meninggal dunia dua tahun yang lalu. Hari ini, ulang tahun kematiannya, Sam. Jika waktu mengijinkanmu, mampirlah sejenak di rumah kami sekedar melawati makamnya. Maafkanlah kami karena merahasiakannya kepadamu selama ini. Salam, Ayah dan Ibu.”
Mendadak kepala saya menjadi pening. Entah apa yang sedang melintas dalam kepala, saya sendiri tidak kuasa membahasakannya.
“Kamu sehat-sehat saja kan?” tanya Ibu dengan nada khawatir.
“Iya, Bu. Saya tidak apa-apa.”
“Sejak kapan kamu suka minum kopi?” kembali Ibu bertanya dengan nada curiga.
“Entahlah, Bu.”
________________________
Ketika cerita ini ditulis, saya sedang berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa sosok yang mengusik pikiran saya selama ini sesungguhnya adalah Sisilia. Bukan roh, apalagi arwahnya.
Jika tidak, betapa kejamnya gadis yang dengan seenaknya berkeliaran dalam kepala saya itu. Atau jika pembaca tahu, kira-kira bagaimana caranya menghidupi kenangan-kenangan, tolong kabarkan kepada saya pula cara untuk mewafatkannya.
Maumere, 2014.
*Diterbitkan di Suara NTB, pada 28 Maret 2015.



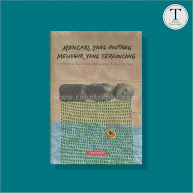
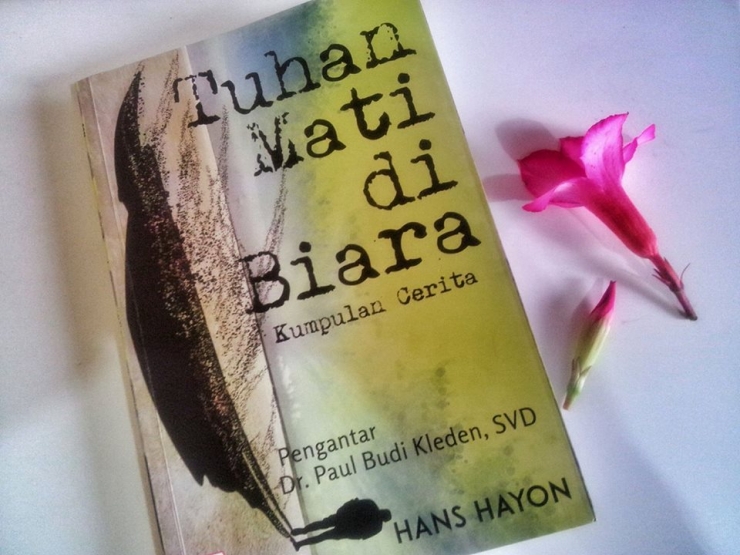

Post a Comment
Post a Comment