Postrukturalisme adalah seni mengelola paradoks. Ia seperti rasa sakit pada gigi yang dapat dilawan dengan cara menggigit. Ia seperti rasa sakit yang inheren dalam cinta. Atau luka yang ditawarkan oleh duri di sekujur tubuh mawar.
Tetapi dari situlah, mau tidak mau, manusia mesti memilih: antara kebaikan dan kejahatan, antara cinta dan benci, antara perang dan damai
Di hadapan semuanya itu, kita sebenarnya sedang bermain-main dengan ketidakpastian.
Postrukturalisme merupakan respon intelektual terhadap strukturalisme. Meskipun dikenal sebagai sebuah istilah yang lebih condong ke bidang kajian linguistik, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa strukturalisme merupakan sebuah paham yang menilai bahwa hubungan antara unsur satu dan unsur yang lain lebih penting daripada unsur itu sendiri.
Konsekuensinya, makna sebuah benda misalnya, dinilai berdasarkan relasi sinkronis dengan apa saja di luar dirinya. Atau yang umum dikenal sebagai signifier (penanda) dan signified (petanda).
Petanda ‘kebahagiaan’ hidup ditemukan dalam penanda seperti menikah, memiliki istri yang cantik, dan dua anak kembar yang lucu; petanda ‘sukses’ ditunjukkan melalui penanda lulus cum laude, bekerja di perusahan besar, dan dengan sedikit menjilat bisa dapat promosi jabatan. Petanda ‘Katolik’ ditampilkan melalui penanda rajin ke gereja, taat perintah orangtua, tidak telat bayar iuran pastoral, dan selalu memberi pipi kiri ketika seseorang menampar pipi kanan.
Hadir sebagai strategi pembanding, postrukturalisme membongkar kemapanan sistem makna tersebut melalui projek filosofis-politis bernama ‘dekonstruksi’ dari Jacques Derrida.
Celakanya, alih-alih membongkar yang lama, Derrida sama sekali tidak menawarkan upaya menyusun kembali apa-apa yang sudah dibongkar. Semua reruntuhan itu dibiarkan begitu saja. Lalu kita diajak bermain-main dengan ketidakpastian, keremang-remangan, kegagalan, dan keragu-raguan.
Felix Nesi, dalam kebanyakan karya fiksinya (terutama cerita pendek) dan tentu saja novel Orang-Orang Oetimu (O3) berada dalam pusaran ini.
Saya tidak berani menyebut novel ini sebagai sebuah kecenderungan posmodernisme ketika di mana-mana orang mencampuradukan antara gaya dan tema penulisan. Sebaliknya, saya menganggap karya fiksi etnografis (mengutip Dewan Juri Novel DKJ 2018) tersebut sebagai sebuah kerja postrukturalis. Ketika di mana-mana, setiap karya ditulis dengan tendensi menggurui pembacanya dengan pelbagai pesan moral tentang kebaikan, cinta kasih, dan perdamaian, O3 justru menjelma gelanggang pertarungan.
Artinya, setiap pembaca diberi kebebasan etis untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya.
Tepat pada level itulah, terjadi pelampauan paling radikal. Lalu lahirlah subjek yang menunda hukum, menunda tatanan sosial, menunda signified. Subjek orang Oetimu yang otentik.
Postrukturalisme merupakan respon intelektual terhadap strukturalisme. Meskipun dikenal sebagai sebuah istilah yang lebih condong ke bidang kajian linguistik, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa strukturalisme merupakan sebuah paham yang menilai bahwa hubungan antara unsur satu dan unsur yang lain lebih penting daripada unsur itu sendiri.
Konsekuensinya, makna sebuah benda misalnya, dinilai berdasarkan relasi sinkronis dengan apa saja di luar dirinya. Atau yang umum dikenal sebagai signifier (penanda) dan signified (petanda).
Petanda ‘kebahagiaan’ hidup ditemukan dalam penanda seperti menikah, memiliki istri yang cantik, dan dua anak kembar yang lucu; petanda ‘sukses’ ditunjukkan melalui penanda lulus cum laude, bekerja di perusahan besar, dan dengan sedikit menjilat bisa dapat promosi jabatan. Petanda ‘Katolik’ ditampilkan melalui penanda rajin ke gereja, taat perintah orangtua, tidak telat bayar iuran pastoral, dan selalu memberi pipi kiri ketika seseorang menampar pipi kanan.
Hadir sebagai strategi pembanding, postrukturalisme membongkar kemapanan sistem makna tersebut melalui projek filosofis-politis bernama ‘dekonstruksi’ dari Jacques Derrida.
Celakanya, alih-alih membongkar yang lama, Derrida sama sekali tidak menawarkan upaya menyusun kembali apa-apa yang sudah dibongkar. Semua reruntuhan itu dibiarkan begitu saja. Lalu kita diajak bermain-main dengan ketidakpastian, keremang-remangan, kegagalan, dan keragu-raguan.
Felix Nesi, dalam kebanyakan karya fiksinya (terutama cerita pendek) dan tentu saja novel Orang-Orang Oetimu (O3) berada dalam pusaran ini.
Saya tidak berani menyebut novel ini sebagai sebuah kecenderungan posmodernisme ketika di mana-mana orang mencampuradukan antara gaya dan tema penulisan. Sebaliknya, saya menganggap karya fiksi etnografis (mengutip Dewan Juri Novel DKJ 2018) tersebut sebagai sebuah kerja postrukturalis. Ketika di mana-mana, setiap karya ditulis dengan tendensi menggurui pembacanya dengan pelbagai pesan moral tentang kebaikan, cinta kasih, dan perdamaian, O3 justru menjelma gelanggang pertarungan.
Artinya, setiap pembaca diberi kebebasan etis untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya.
Tepat pada level itulah, terjadi pelampauan paling radikal. Lalu lahirlah subjek yang menunda hukum, menunda tatanan sosial, menunda signified. Subjek orang Oetimu yang otentik.
Siapa tahu. Mungkin juga orang NTT sekaligus orang Indonesia yang otentik.
Pengamatan Sekilas
Novel itu terdiri atas 220 halaman, lebih tipis dari minat saya membaca karya Felix.
Sampul depannya dipenuhi beberapa gambar kunci antara lain: bangunan gereja (karena ada salib di atasnya), seorang petani, perempuan yang berlari, dua orang berciuman, enam botol minuman, dua ekor hewan bertanduk, seorang lelaki berjalan sambil membawa pentungan (mungkin polisi atau aparat), pejabat gereja (pastor dan suster), dan dua orang melayang di udara dengan kaki terangkat (mungkin sedang berkelahi).
Sebelum membaca, saya menghabiskan beberapa menit mereka-reka maksud pemilihan gambar-gambar tersebut dan mafhum. Bagaimana mungkin Felix menggarap beberapa tema penting dalam novel setipis ini? Jika tidak diimbangi dengan teknik menulis yang canggih, novel ini tentu akan sangat membosankan seperti kebanyakan novel yang ditulis oleh penulis NTT akhir-akhir ini.
Rupanya Marjin Kiri bukanlah sembarang penerbit. Kalau bukan dengan doa, demikian saya membatin, sampul buku itu pasti dikerjakan dengan kecedasan artistik yang tidak biasa.
Dan Felix bukanlah sembarang penulis. Enggan menerbitkan novel Pemenang I Sayembara Novvel DKJ 2018 di Penerbit Gramedia merupakan pilihan politis dan sosiologis yang perlu diapresiasi.
Saya tahu, ia tidak sekadar menulis. Felix berdoa melalui kerja-kerja ideologis.
Dengan menggunakan beberapa tokoh kunci, O3 menggambarkan dengan begitu bagus bagaimana masyarakat Oetimu hidup di bawah pengaruh global yang luar biasa terutama kolonialisme Indonesia di Timor-Timur (sekarang Timor Leste).
Tokoh-tokoh seperti Silvi yang cerdas tetapi rapuh, Pastor Yosef yang kelihatan tegar untuk menyembunyikan disposisi batinnya yang kalut, Sersan Ipi yang disiplin, patuh, dan kesepian, Martin Karbit yang kurang bertanggung jawab dan beruntung, Ayah Silvi yang sial, dan Maria yang putus asa karena terlampau kritis, adalah gambaran manusia pada umumnya. Manusia yang senantiasa bertarung sebelum menentukan pilihannya.
Meskipun tidak semua perjuangan berakhir bahagia, O3 menawarkan dimensi etis lain. Perjuangan, itulah tujuan, bukan hasilnya. Di situ, pembaca yang selama ini dimanjakan oleh ending yang konvensional dan tidak bermutu, tentu akan dibuat kesal. Itulah postrukturalisme.
Mengutip Claude Lefort, inilah sebuah ketakterputusan radikal. Sebab, ketika semua cerita memiliki ending, hidup adalah cerita tanpa akhir.
Status Paradoks dan Dimensi Etis Para Tokoh
Semua orang tahu apa itu moral namun sedikit saja yang mengerti apa itu etika.
O3 ditulis dalam terang dimensi kedua di mana para tokohnya dibiarkan hidup dan berkembang berdasarkan pilihan-pilihannya sendiri. Meskipun kadang gagal, setidaknya mereka telah berani memilih.
Maria contohnya. Perempuan itu akhirnya memilih bunuh diri meskipun pernah melontarkan godaan bahwa dengan hidup bersama frater Yosef, mereka bisa melahirkan kembali Tuhan. Di hadapan tindakan seperti itu, tatanan moral dan hukum tidak berati.
Maria, pada level tertinggi, bertindak melampaui dirinya sendiri, melampau imajinasi agama dan negara tentang bagaimana hendaknya menjadi seorang perempuan. Pada akhirnya, ia menunda bahasa.
Tindakannya adalah kata-kata itu sendiri.
O3 ditulis dengan gaya seperti di atas. Deksripsi kuat sambil tetap menjaga detail dan analitis. Meskipun mengandung anasir-anasir preskriptif yang mendorong pembaca untuk melakukan sesuatu, namun itu disembunyikan secara licin, tepat di hadapan mata kita sendiri.
Bandingkan deskripsi seperti di bawah ini:
Om Pati yang baru pulang dari tanah jawa memperkenalkan lapangan kerja baru, yaitu mengantar orang dengan sepeda motor dan meminta uang sebagai gantinya. Anak-anak muda yang enggan menggarap kebun, mengajukan cicilan sepeda motor dengan jaminan sertifikat tanah, dan mulai mengangkut penumpang. Namun, orang Oetimu lebih suka berjalan kaki atau naik kuda, sehingga anak-anal muda itu lebih banyak nongkrong di pangkalan ojek, minum-minum sambil main catur (halaman 58).
Tanpa harus berlagak seperti penjaga moral, O3 tidak otomatis menghakimi para pemuda tukang ojek sebagai pengangguran dan kumpulan manusia dari generasi yang tidak berguna.
Ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada urusan moralitas: kapitalisme dan neoliberalisme.
Gaya bekerja dengan mengandalkan bursa jasa yang marak di Jawa dan daerah maju lainnya merangsek masuk hingga ke pelosok Timor melalui sistem keparat bernama liberalisasi ekonomi kapitalis.
Akibatnya, cara berpikir dan bertindak orang Oetimu meniru cara berpikir daerah maju.
Bahkan cita-cita seorang anak kecil direkayasa sedemikian rupa demi memenuhi fantasi masyarakat pada umumnya tentang apa itu kemajuan dan cita-cita yang benar.
Bandingkan deskripsi berikut:
Jon, mau jadi apa kau kalau sudah besar nanti? Polisi, pastor, atau pegawai kantor pajak?”
Maka Jon kecil itu akan menjawab dengan mantap: “saya mau menjadi siswa di SMA Santa Helena.
Mendengar itu setiap orang pun akan memuji cita-cita mulia si Jon kecil (halaman 99)
Itu bukan pilihan otomatis. Pilihan itu lahir dari pengamatan seorang anak kecil terhadap perilaku masyarakatnya yang tergila-gila pada SMA Santa Helena yang bertaraf nasional dan internasional itu.
Namun cita-cita, bagi sebagian masyarakat kelas bawah dengan penghasilan yang kerdil, tidak lebih dari ilusi. Biaya pendidikan yang mahal terpaksa membuat anak-anak harus puas diri dengan kenyataan bahwa tanpa uang semua hal tidak berguna.
Lama-kelamana mereka benar-benar berhenti bersekolah. Yang perempuan menjadi pelacur usia dini dan yang laki-laki bekerja penuh waktu sebagai pencari pakan untuk sapi di karantina. Mereka harus menerima kenyataan, bahwa untuk menjadi cerdas, mereka membutuhkan uang. Sopir angkot hanya mau mengantar ke sekolah bila dikasih uang. Guru-guru pun hanya mau mengajar jika dikasih uang. Namun uang tidak gampang dicari. Hanya daun yang gampang dicari. Dan hanya sapi, di karantina itu, yang mau dikasih daun (halaman 100).
Meskipun demikian, tidak semua orang lekas menerima kekalahan. Dari sungut-sungut kecil yang sering diocehkan Am Siki hingga umpatan Maria, membuktikan bahwa benih perlawanan selalu ada.
Sekalipun sistem bersifat totaliter, ia tidak pernah total dan absolut. Seperti kritik yang dilontarkan sesudah penetapan agama formal di Indonesia atau pemberlakukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi contohnya.
Maka sesaklah dada Am Siki. Ia menjadi bersedih hati, sebab orang-orang asing itu selalu datang silih berganti, tetapi tak ada satu pun yang mau belajar berbicara dengan bagasa yang baik dan benar. Selalu saja orang-orang Timor yang dipaksa untuk mempelajari arti dan bunyi-bunyi aneh yang keluar dari mulutnya: mulai dari Portugis, Belanda, Jepang, sampai Indonesia (halaman 39).
Perilaku meniru-niru gaya hidup daerah perkotaan berkelindan dengan standar kebijakan politik terutama kebijakan sosial ekonomi terutama pada masa Soeharto memerintah.
Dengan menekankan logika pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keamanan, segala sesuatu dirumuskan dari perspektif Jakarta. Di bidang pangan disebut swasembada beras dan di bidang kultural, beradab berarti hidup berdasarkan standar-standar Jakarta. Imbasnya, meskipun tidak mempunyai sawah dan mereka menanam jagung dan singkong di ladangnya, makanan pokok orang Oetimu adalah nasi.
Sistem seperti itu juga merasuk dalam institusi raksasa di level lokal yakni Gereja.
Saya tahu bahwa penulis O3 pernah mengenyam pendidikan di Seminari Lalian dan tentu ia tahu seluk beluk bagaimana institusi gereja bekerja.
Teknik serupa juga menjelma dalam bentuk permohonan sumbangan. Alih-alih membangun strategi alternatif mengadang sistem kapitalisme dan neoliberalisme, gereja cenderung menggantungkan harapannya pada frasa yang diulang-ulang dalam kitab suci, “belas kasihan” (orang kaya).
Dengan demikian, makin lengkaplah kesengsaraan masyarakat karena negara, gereja, dan kultur berhasil dikooptasi secara habis-habisan.
Bukannya mengkritik dan mengubah sistem, wacana yang dipakai untuk mengentas kemiskinan dan kesengsaraan adalah sistem moral.
Alih-alih mengkritik kemapanan institusi gereja, opini masyarakat justru digiring untuk mengkritik perilaku seksual pastor.
Sebenarnya saya bisa menahan diri untuk menulis ulasan yang lebih sistematis mengenai tema tertentu dalam O3 ini. Namun, karena besarnya harapan saya agar buku ini dibaca oleh semua orang, khususnya orang NTT, saya menulis ulasan singkat dan tidak bermutu ini.
Awalnya, saya ingin menulis tema teologi politik namun kandas karena keterbatasan waktu (maafkan, Felix). Semoga pembaca berkenan memaafkan ketergesa-gesaan saya tersebut.
Bapak-Bapak dan Ibu-ibu, seluruh penduduk yang pandai dan sehat. Musim panen telah tiba. Kita semua akan memanen jagung dan singkong. Namun tahukah Anda, apa itu jagung dan apa itu singkong? Jagung dan singkong adalah makanan nenek moyang kita. Nenek moyang kita bodoh dan punya gizi yang buruk, sebab mereka hanya makan jagung dan singkong. Sudah ada penelitian dari Barat, bahwa dua makanan itu memiliki zat yang hanya bikin otak menjadi lemah. Ia tidak punya gizi apa-apa.
Maka dari itu, Bapak dan Ibu sekalian, jangan biarkan kita mewarisi kebiasaan yang salah dan keliru itu. Mari, kita mulai makan nasi. Kita harus makan nasi, agar kita dan anak-anak kita menjadi manusia yang lebih berbudaya, lebih beradab, dan senantiasa beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai sila pertama Pancasila.” (halaman 55-56)
Sistem seperti itu juga merasuk dalam institusi raksasa di level lokal yakni Gereja.
Saya tahu bahwa penulis O3 pernah mengenyam pendidikan di Seminari Lalian dan tentu ia tahu seluk beluk bagaimana institusi gereja bekerja.
Di hadapan sistem kapitalisme global, gereja tidak luput dari pengaruhnya. Ocehan tentang lahan basah (pindahnya Romo Yosef dari paroki Santo Ferdinandus di jantung kita ke SMA Santa Helena di pesisir teluk Kupang) menunjukkan hal tersebut (halaman 90-91).
Teknik serupa juga menjelma dalam bentuk permohonan sumbangan. Alih-alih membangun strategi alternatif mengadang sistem kapitalisme dan neoliberalisme, gereja cenderung menggantungkan harapannya pada frasa yang diulang-ulang dalam kitab suci, “belas kasihan” (orang kaya).
Tidak lebih dari seminggu, Romo Yosef telah mendapatkan sangat banyak donasi, baik dari pengusaha yang jujur maupun tidak jujur, maupun dari pejabat negara yang menipu sedikit maupun yang menipu banyak (halaman 95).
Dengan demikian, makin lengkaplah kesengsaraan masyarakat karena negara, gereja, dan kultur berhasil dikooptasi secara habis-habisan.
Bukannya mengkritik dan mengubah sistem, wacana yang dipakai untuk mengentas kemiskinan dan kesengsaraan adalah sistem moral.
Alih-alih mengkritik kemapanan institusi gereja, opini masyarakat justru digiring untuk mengkritik perilaku seksual pastor.
Di suatu Desember yang mendung, seorang kawan Maria, Elisabeth, mencoba menggugurkan kandungannya, mengalami pendarahan dan hampir mati. Sambil menangis, Elisabeth bercerita, ia aktif di organisasi orang muda Katolik dan telah lama ditiduri oleh pendamping mereka, seorang romo yang berusia tiga puluhan…. Agnes pernah bertukar rayu dengan Romo Agus; Ira sering menjawab telepon mesum dari Romo Rafael, Romo Binus pernah mengap-mengap sesudah meminta Yani berjongkok di selangkangannya (halaman 153-155).
Sebenarnya saya bisa menahan diri untuk menulis ulasan yang lebih sistematis mengenai tema tertentu dalam O3 ini. Namun, karena besarnya harapan saya agar buku ini dibaca oleh semua orang, khususnya orang NTT, saya menulis ulasan singkat dan tidak bermutu ini.
Awalnya, saya ingin menulis tema teologi politik namun kandas karena keterbatasan waktu (maafkan, Felix). Semoga pembaca berkenan memaafkan ketergesa-gesaan saya tersebut.



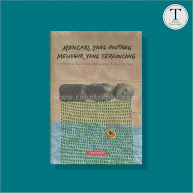
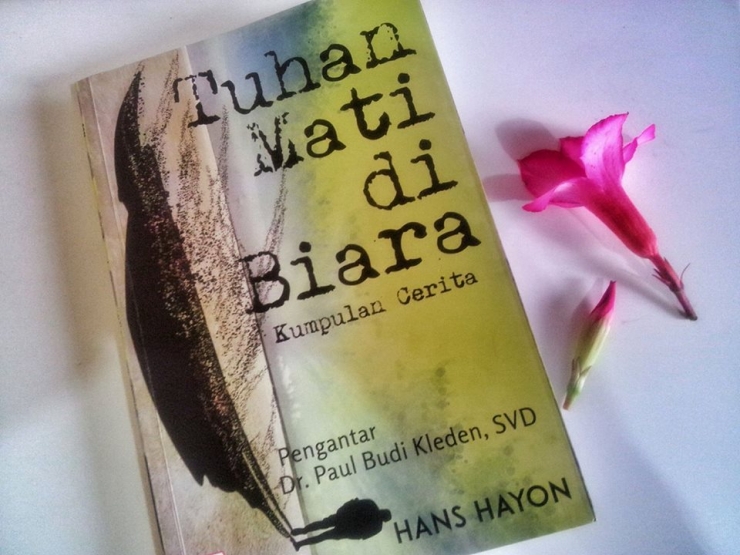

Post a Comment
Post a Comment