(Judul di atas menjadi judul buku kumcer Tuhan Mati di Biara)
 |
| Salah satu adegan dalam film "The Nun". Dalam film tersebut, tampak Taissa Farmiga berperan sebagai biarawati Irene. Sumber foto: Kincir.com |
2000
Mungkin akulah wanita pertama yang berani menangis karena sebuah biara. Kegeramanku memuncak saat panggilanku makin sekarat hanya karena lilitan aturan hidup yang baku dan aku.
Aturan yang membuatku terpaksa beranjak pergi, sebelum jatuh ke dalam pelukan pemuda tetangga sebelah.
Apakah ini sebuah dosa? Apakah mencintai itu sebuah dosa? Yang lebih tua itu cinta ataukah agama? Tuhan itu sesuatu ataukah seseorang?
Sesudah menemukan kebuntuan atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial tersebut, aku putuskan untuk mengakhiri ziarah panggilanku sebagai seorang biarawati.
Hal yang lumrah bukan, jika seorang wanita sepertiku melakukan hal demikian dalam situasi terjepit?
Jawaban kalian menentukan masa depan Gereja Katolik di dunia. Mungkin juga masa depanku.
***
1999
Setelah lima tahun menjalani hidup sebagai seorang wanita desa, Grace akhirnya kembali jatuh cinta. Kali ini, pemuda berwajah tampan itu berhasil meluluhkan hatinya, ketika untuk kesekian kalinya mereka berpapasan selepas perayaan Ekaristi di Gereja Hati Kudus Yesus-Nita.
Di setiap larik doa yang tersembul dari gemetar bibir umat, terselip harap sentosa bersama tatapan panjang tanpa kedip. Grace gagal terpana.
Gerbang neraka seakan melebar pada cinta jenis ini. Cinta yang diharamkan oleh agama, masyarakat, tradisi, dan mungkin Tuhan juga.
Grace hanya sanggup menafsir jawab dalam kebingungan yang melangit.
Rasanya gejolak yang bertumbuh, kini terlalu kokoh untuk dirobohkan oleh tradisi gaya berpikir konservatif seperti itu. Bahkan oleh maut sekalipun, gemetar terhadapnya.
“Aku mencintaimu setelah tak tahu bagaimana harus menyesali perasaan itu,” ujar Grace ragu, ketika lonceng gereja berdentang pertama kali tepat pkl. 06.00 WITA.
“Sulit kutebak! Kamu mencintai seseorang ataukah sesuatu dari seseorang?” gugat lelaki itu serius.
“Aku mencintaimu karena aku mencintaimu.”
“Kamu cenderung bersembunyi di balik tautologi itu. Seandainya aku, mungkin tidak!” jawab lelaki itu pergi, setelah meninggalkan sesungging senyuman.
Grace sadar. Zaman ini, ketika cinta ditertibkan, benci semakin dikoordinasi. Sebuah zaman di mana segala sesuatu patuh berjalan sesuai aturan, nilai, dan hukum yang berlaku universal.
Tertinggal perasaan dan gerutu tiada akhir tentang sesuatu yang dideritanya saat ini: mencintai sebuah dosa.
“Apa? Kamu benar-benar mencintainya?” tanya Ratih, sahabat karib Grace.
Lebih tepatnya, Ratih adalah kawan curhat ketika ia dilanda persoalan hidup terutama yang berhubungan dengan perasaan dan degup tak karuan jantungnya. Selalu saja Ratih menjadi tumpuan amuk gelora badai di hatinya.
“Cinta tak selalu mengenal kata serius, kan? Aku hanya tak ingin menderita terlalu lama karena perasaan ini. Itu saja.”
“Ya Tuhan, Grace. Sadarlah! Segala sesuatu ada hukumnya, sayang.” Ratih coba meyakinkan bahwa wanita itu sedang dalam sebuah kesalahan yang fatal.
“Jika demikian, aku berpikir: hukum juga demi cinta, bukan?” bantah Grace kritis.
“Kamu tahu, Grace? Diskusi terberat dalam hidup ini yang solusinya adalah tanpa solusi ialah tentang perasaan dan mimpi-mimpi,” imbuh Ratih pasrah.
Malam sepekat kopi, ketika keduanya larut dalam pikiran masing-masing. Berharap esok pagi, kemelut itu raib bersama hilangnya kelam.
Tak ada yang tahu, bagaimana cinta itu melangkah, berjalan, dan pergi. Yang mereka tahu hanyalah kesadaran bahwa mereka tidak selalu betul-betul memilikinya.
Andai saja Tuhan hidup di zaman ini, Ia pasti kaget keesokan harinya: Ia tidak bisa datang dan pergi sesuka hati-Nya.
Ketika pagi belum terlalu dewasa, betapa kagetnya Ratih saat menemukan Grace tak ada. Dengan tergesa, ia berlari mendatangi beberapa kerabatnya namun hasilnya mubazir.
Grace menghilang entah ke mana.
Karena letih, Ratih akhirnya kembali ke penginapannya dengan rasa bersalah. Dihempaskan tubuhnya pada sebuah kursi malas, sebelum matanya menangkap sebuah guratan pada kertas, tergeletak tepat di atas meja belajarnya.
Di dunia ini, sebenarnya tidak ada jarak
Jatuh cinta, pertemuan, dan perpisahan
Hanyalah perasaan.
“Ya Tuhan! Ini tulisan tangannya,” batin Ratih sambil berlalari menuju pantai yang letaknya tak jauh amat dari rumah.
Sebuah senyum perlahan tersembul di bibirnya, ketika sirene kapal rute Maumere-Makassar menjerit tiga kali.
***
2013
“Berdasarkan berita acara persidangan hari ini, Senin, 19 Agustus 2013, Sdr. Lukas Sabtu dijerat Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Pasal 181 KUHP jo 65 Ayat 1 KUHP tentang menguburkan mayat sebagai tindakan menghilangkan barang bukti maka keputusan yang sesuai adalah penjara seumur hidup.”
Suara hakim terdengar membahana, disusul teriakan massa, “Hukum mati saja!”
Persidangan pun usai setelah air mataku kembali menetes dengan ikhlas. Aku sendiri tahu persis kejadiannya, dan apakah saudara terdakwa itu pantas dihukum demikian ataukah tidak. Sayang, suaraku tak cukup kuat mereka inderai, bahkan oleh telingaku sendiri.
Terhampar begitu saja di depan mata, perjalanan hidupku yang kian hancur: Wanita sundal yang malang. Kalimat yang sering kudengar bila sedang berpapasan dengan orang kebanyakan di emperan toko, lembaga LSM, biara-biara, rumah sakit, dan tempat ibadah.
Mungkin inilah takdirku sebagai seorang wanita yang terjebak dalam tradisi.
“Maafkan aku, suamiku. Aku hanya sanggup menatapmu dari tempat ini tanpa berbuat banyak untuk menolongmu,” keluhku lirih saat terdakwa digiring ke luar ruangan.
Dengan cekatan kuseka air mata yang tumpah, saat seorang gadis kecil mendekatiku dari samping.
“Kenapa Ibu menangis?” tanya gadis itu polos.
“Tidak apa-apa, nak,” jawabku sekenanya sambil memaksa diri untuk tersenyum.
“Tapi kan, ada air matanya?” Kembali gadis kecil itu bertanya dengan nada memrotes.
Sebelum sempat kujawab pertanyaannya, terdengar suara berat dari arah belakangku.
“Tinny, dengan siapa kamu bicara?”
“Dengan Ibu ini, Ayah” jawab gadis itu sambil menggandeng tanganku.
“Ibu? Tidak ada siapa-siapa di sini, nak," ujar lelaki tua itu sambil menarik tangan anaknya, "Ayo pulang!”
(Maumere, Agustus-September 2013).


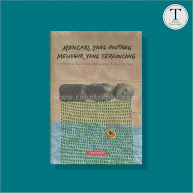
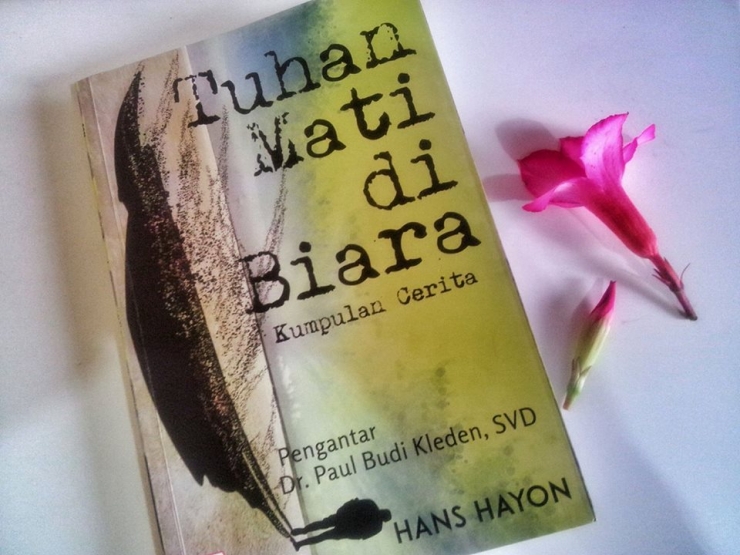

Post a Comment
Post a Comment