Only an atheist can be a good Christian;(Dies septimus nos ipsi erimus,—Agustine)
only a Christian can be a good atheist
Pengantar
Tri Hari Suci yang terdiri atas Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci (malam Paskah) merupakan momen paling krusial di mana Allah berupaya menerjemahkan gagasan keselamatan melalui cara-cara manusia. Pada hari-hari tersebut, terdapat dua peristiwa kunci yakni kematian dan kebangkitan Allah yang selanjutnya menjadi inti iman dalam kristianitas.
Ketika Yesus wafat di salib, terjadi kematian di dalam Allah. Kematian ini dimengerti sebagai terputusnya rantai signifikasi (chain of signification) atau rantai penandaan yang, hanya dengan cara itulah, terdapat adanya kemungkinan mengenal dan memahami Allah.
Dengan kata lain, pemahaman akan Allah sebagai “Yang Maha Kuasa” dicapai justru melalui tahap signifikasi, atau meminjam term psikoanalisa Jacques Lacan, sebagai The Symbolic. Dikatakan demikian karena meskipun Allah hadir secara konkret (melalui inkarnasi dalam diri Yesus) hic et nunc, umat kristen memahami-Nya secara Trinitarian sebagai bentuk revelasi dari The Real (Allah Bapa).
Oleh karena itu, mengutip Hegel, Žižek mengatakan bahwa apa yang mati di salib bukan hanya inkarnasi representatif dari Allah duniawi melainkan Allah di dalam dirinya sendiri.
Momentum kematian Allah merupakan saat di mana Allah akhirnya absen. Meskipun demikian, absennya Allah itu, kata Emanuel Levinas, bukanlah ketidakhadiran yang tanpa makna (Purcell, 2006:66) melainkan melalui cara itu, Allah coba memberikan kesempatan kepada manusia untuk mengambil tindakan.
Selanjutnya, Allah yang absen itu bekerja dalam komunitas beriman. Oleh sebab itu, Žižek menulis bahwa Christ is the “vanishing mediator” between the substantial transcendent God-in-itself and God qua virtual spiritual community (Žižek dalam Davies, 2009:29). Namun, tidak jarang komunitas beriman terjebak dalam situasi yang sama dengan Allah dan seruan Yesus di atas salib, “Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Aku” juga dipekikan oleh manusia.
Hal ini tampak misalnya dalam keluhan semisal, “Berapa lama lagi, Tuhan, Kaulupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kausembunyikan wajah-Mu terhadap aku?” (Mazmur 13:1-3). Atau, “Tetapi aku ini, ya Tuhan, kepada-Mu aku berteriak minta tolong. Mengapa, ya Tuhan, Kaubuang aku, Kausembunyikan wajah-Mu dari padaku” (Mazmur 88:14-15).
Cukup beruntung bahwa kematian sebagai peristiwa terputusnya rantai penandaan digantikan dengan penanda baru yakni kebangkitan dalam chain of signifier bernama keselamatan. Hal yang sama juga berlaku dalam diri Allah. Oleh karena itu, apa yang kita miliki setelah peristiwa penyaliban dan kebangkitan Allah, bukan Allah Bapa atau Allah Putra, melainkan Roh Kudus.
Dan kitab suci menulis bahwa Roh Kudus adalah cinta diantara orang-orang beriman—inilah semangat dasar dari komunitas kaum beriman. Pernyatan terkenal Yesus: sebab dimana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka (Matius 18:20).
Maksudnya, sebagai umat beriman, melalui meterai pembaptisan, kita menerima tugas perutusan yang sama. Hadirnya Roh Kudus dalam wujud eksplisit kemampuan berbahasa merupakan simbolisme dari trajektori politik diferensiasi dan multikulturalisme.
Di situ, kebangkitan secara preskriptif mengandung dimensi pengakuan terhadap diri sendiri dan orang lain.
Dengan bantuan dua pemikir antara lain Slavoj Žižek dan Emanuel Levinas, tulisan ini mencoba mengambil relevansi narasi Kitab Suci tentang Allah terhadap kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
Pada Žižek sebagai intelektual ateis militan, gagasannya merepresentasikan materialisme kritis melawan ilusi agama yang dimulai dari Hegel, Marx dan Feuerbach dan tradisi strukturalisme Prancis yang kemudian memuncak pada Louis Althusser dan Jacques Lacan.
Sementara itu, pada Levinas sebagai filsuf dari tradisi fenomenologi sekaligus intelektual agama Yahudi, ia berupaya membaca gagasan Allah dengan cara transendensi.
Sekurang-kurangnya gagasan utama Levinas adalah bahwa: pertama, dia sepakat dengan transendensi tentang yang ilahi namun, kedua, yang lebih penting, karena ia menjadikan Allah sebagai objek studi, yang menghindari jalan memutar tentang manusia. Levinas juga tidak percaya terhadap semua mistisisme yang mencari akses terhadap Tuhan tanpa perjumpaan dengan manusia. Bagi Levinas, Tuhan hanya bisa dialami dalam diri manusia.
Dari dua teoretikus inilah, saya coba membaca teologi politik dan demokrasi dari perspektif sejarah hidup Yesus. Tentu saja saya tidak memahami teologi politik sebagai sebuah paradigma berpikir yang berupaya merespon cercaan para ateis, anarkis (Proudhon dan Mikhail Bakunin), dan ilmuwan positivistik (Comte).
Dengan bantuan dua pemikir antara lain Slavoj Žižek dan Emanuel Levinas, tulisan ini mencoba mengambil relevansi narasi Kitab Suci tentang Allah terhadap kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
Pada Žižek sebagai intelektual ateis militan, gagasannya merepresentasikan materialisme kritis melawan ilusi agama yang dimulai dari Hegel, Marx dan Feuerbach dan tradisi strukturalisme Prancis yang kemudian memuncak pada Louis Althusser dan Jacques Lacan.
Sementara itu, pada Levinas sebagai filsuf dari tradisi fenomenologi sekaligus intelektual agama Yahudi, ia berupaya membaca gagasan Allah dengan cara transendensi.
Sekurang-kurangnya gagasan utama Levinas adalah bahwa: pertama, dia sepakat dengan transendensi tentang yang ilahi namun, kedua, yang lebih penting, karena ia menjadikan Allah sebagai objek studi, yang menghindari jalan memutar tentang manusia. Levinas juga tidak percaya terhadap semua mistisisme yang mencari akses terhadap Tuhan tanpa perjumpaan dengan manusia. Bagi Levinas, Tuhan hanya bisa dialami dalam diri manusia.
Dari dua teoretikus inilah, saya coba membaca teologi politik dan demokrasi dari perspektif sejarah hidup Yesus. Tentu saja saya tidak memahami teologi politik sebagai sebuah paradigma berpikir yang berupaya merespon cercaan para ateis, anarkis (Proudhon dan Mikhail Bakunin), dan ilmuwan positivistik (Comte).
Dikatakan demikian karena teologi politik tidak menawarkan model politis berkaitan dengan pengajaran teologis karena jika demikian ia bukan teologi karena wahyu tidak merepresentasikan model rigid sebagaimana sepuluh perintah Allah (Schmitt, 1969:47).
Oleh karena itu, artikel ini akan menunjukkan apa saja relevansi semua penafsiran di atas bagi demokrasi khususnya demokrasi radikal yang menekankan pentingnya posisi sipil dalam kehidupan politik. Selanjutnya, saya juga akan mengkritik model transendental Levinas yang masih mengandalkan metafisika Descartes dan limitasi pendekatan Žižek yang berupaya membawa teologi kepada taraf materialistik.
Sebaliknya, dalam Perjanjian Baru (PB), jembatan mediasi ini dirobohkan terutama dengan hadirnya sosok Yesus melalui inkarnasi. Alih-alih bertindak sebagai outsider, Allah dalam PB bertindak secara ekstrim dan memilih cara hidup sebagai manusia bahkan sampai mati di salib. Allah PB melambangkan Allah yang rentan. Dikatakan demikian karena Allah jenis ini benar-benar dapat diinderai asal-usulnya, tempat tinggalnya, tempat kelahirannya, ibu dan ayahnya dan garis keturunannya.
Kalau mau jujur, kristinanitas merupakan satu-satunya agama di dunia yang melihat kekuasaan sebagai hal yang membuat Allah tidak lengkap bahkan rentan. Akibatnya, Allah (Allah secara keseluruhan) dilihat sekaligus sebagai seorang pemberontak dan raja (Žižek dalam Davies, 2009:237).
Ketidaklengkapan Allah ini dimulai dari adanya proses sekularisasi dalam sejarah Eropa modern yang menghapus Allah metafisis cum moral dari onto-teologi, dan secara paradoks membuka ruang bagi agama post-metafisik yang otentik, sebuah kekristenan yang fokus pada Kasih.
Dalam PL, keselamtan bersifat partikular dan esklusif, hanya dikhususkan kepada bangsa Israel (as chosen people). Di situ, dominasi kaum laki-laki sangat signifikan sebagai kelas yang paling berkuasa menentukan keselamatan bangsa. Akibatnya, manusia PL adalah manusia yang teralienasi karena mengandalkan apa yang disebut oleh Hegel dan Marx sebagai subjek moral dan karena itu dideterminasi oleh dunia objektif.
Sementara itu, pada PB, keselamatan menjangkau semua orang, tidak terbatas pada apakah orang Yahudi atau bukan, bersunat atau tidak. Ada upaya memberi tempat bagi “Other” yang secara eksplisit digambarkan dalam peristiwa “Perempuan Samaria”. Bahkan, dalam peristiwa kebangkitan, sosok pertama yang menerima kabar tersebut secara langsung dari Yesus adalah perempuan bernama Maria Magdalena. Itu berarti keselamatan bukan lagi sebuah kerja individual sebagaimana dalam PL melainkan kerja kolektif. Dikatakan demikian karena 'belief in God is not a singular or individual enterprise, but is intersubjective and communitarian' (Purcell, 2006:60).
Jika merujuk pada pemikir kristen Agustinus, terdapat kepercayaan bahwa ide tentang “Self” senantiasa terpisah sebelum beristirahat dengan damai dalam Allah. Bagi Agustinus, tidak ada subjek otonom atau 'cogito' sebagaimana dalam klaim Descartes, “I think, therefore I am”. Ada dua jenis implikasi pemahaman subjek cogito Descartes yakni pertama, yang seluruhnya terpusat di dalam dirinya sendiri (premis dasar dari liberalisme atau “kehendak berkuasa”-nya Nietzsche) dan kedua, subjek yang tampil melawan dunia ekstrenal sekaligus tak tampak (postmetafisika Levinnas, Derrida).
Sambil bereferensi pada kategori terakhir, manusia PB adalah manusia kasih yang berani hidup tanpa politik penandaan absolut dan selalu mengandalkan politik perjumpaan. Itulah alasan mengapa Lacan menegaskan bahwa kasih selalu adalah kasih kepada ‘yang lain’ sejauh karena kekurangan atau keterbatasannya (Žižek dalam Davies, 2009:39). Kesimpulan radikal ini menunjukkan bahwa jika kita mencintai Allah, artinya, seharusnya Allah dibayangkan sebagai sosok yang tidak sempurna dan punya banyak kekurangan, bahkan mengandung inkonsistensi di dalam diri-Nya sendiri. Kasih dalam pengertian ini selaras dengan definisi Derrida tentang hospitalitas sebagai tanggung jawab terhadap ‘yang asing’ dan tidak menyerang ketika mereka memasuki teritori orang lain (Derrida, 2007:2-6).
Era Orde Lama (ORLA) dan Orde Baru (ORBA) memosisikan subjek warga negara dari perspektif nasionalisme sempit sebagai wacana gerakan yang tak jarang terjebak pada logika etnosentrisme dan rasialisme. Di situ, proses saling mengesklusi dianggap sebagai cara paling ampuh mendefinisikan diri, kelompok, dan komunitas melalui frasa Soekarnoisme seperti “ganyang Malaysia” atau kelompok ultra-nasionalis melalui “NKRI Harga Mati”, “Pancasilais”, “Anti-PKI”, dan seterusnya.
Dengan perkembangan digitalisasi yang membuat batas-batas dunia menjadi kabur, logika pembedaan tersebut bekerja dalam domain ideologi. Respon datang dari demokrasi radikal yang menawarkan paradigma baru simetris dengan PB sebagai upaya memberikan tempat bagi “yang lain”, termasuk kaum perempuan, LGBT, dan seterusnya berdasarkan 'subject position'.
PL menekankan strategi pendekatan top-down di mana Allah sebagai otoritas yang memprakarsai projek keselamatan. Sementara itu, pada PB, dengan mengandalkan strategi horizontal (bukan bottom-up), keselamatan merupakan hasil akumulasi dari dialog dengan umat beriman berdasarkan latar belakang pendidikan (ahli Taurat), kelas (orang kaya), dan kultur (perempuan Samaria).
ORBA, melalui projek pembangunan bernama developmentalism, menjadikan relasi pusat dan daerah semata-mata berlangsung dari perspektif nasional. Meskipun reformasi berhasil mengubah ketimpangan struktural ini namun masih ada hal yang absen yakni struktur kesadaran mental sipil. Dengan kata lain, belum ada dialog yang komprehensif antara negara dan sipil. Mempertimbangkan kondisi seperti ini, muncul pertanyaan, bagaimana seharusnya gereja merumuskan model pendekatannya? Schmitt mengutip tulisan E. Piterson bertajuk Theologische Traktate demikian:
Konsep tentang Allah dan Kekuasaan
Allah dalam Perjanjian Lama (PL) adalah persona metafisik yang dapat dijangkau hanya melalui proses signifikasi (penandaan). Itulah alasannya mengapa dibutuhkan para nabi sebagai mediator antara Allah dan manusia. Hal tersebut tercermin dalam teologi dogmatis—yang kemudian dikritik oleh Levinas—di mana pertanyaan tentang Allah dipisahkan dari ikatannya dengan manusia. Akibatnya, teologi menjadi abstrak sekaligus metafisis karena mengandaikan adanya logos murni dan bagi Levinas, which is ‘the most dangerous of abstractions since it is the highest’ (Purcell, 2006:51). Dikatakan demikian karena Allah Abraham, Isak dan Yakob adalah idolatria dari foundasionalisme klasik yang sama sekali tidak memiki pertemuan pribadi dengan manusia secara langsung.Sebaliknya, dalam Perjanjian Baru (PB), jembatan mediasi ini dirobohkan terutama dengan hadirnya sosok Yesus melalui inkarnasi. Alih-alih bertindak sebagai outsider, Allah dalam PB bertindak secara ekstrim dan memilih cara hidup sebagai manusia bahkan sampai mati di salib. Allah PB melambangkan Allah yang rentan. Dikatakan demikian karena Allah jenis ini benar-benar dapat diinderai asal-usulnya, tempat tinggalnya, tempat kelahirannya, ibu dan ayahnya dan garis keturunannya.
Kalau mau jujur, kristinanitas merupakan satu-satunya agama di dunia yang melihat kekuasaan sebagai hal yang membuat Allah tidak lengkap bahkan rentan. Akibatnya, Allah (Allah secara keseluruhan) dilihat sekaligus sebagai seorang pemberontak dan raja (Žižek dalam Davies, 2009:237).
Ketidaklengkapan Allah ini dimulai dari adanya proses sekularisasi dalam sejarah Eropa modern yang menghapus Allah metafisis cum moral dari onto-teologi, dan secara paradoks membuka ruang bagi agama post-metafisik yang otentik, sebuah kekristenan yang fokus pada Kasih.
Dengan demikian, Allah bukan lagi Sang Ada Ilahi yang berdiri di luar sejarah mengamati kehidupan manusia, melainkan dalam keterbukaan yang radikal, terlibat dalam harapan akan perubahan dan selalu datang kepada Otherness. Alasan yang sama digunakan oleh Eckart yang menulis: “…he was big with nothingness as a woman is with a child. In this nothingness God was born. He was the fruit of nothingness. God was born in nothingness” (Žižek dalam Davies, 2009:36).
Dari perspektif Paskah, Allah yang mati dan naik ke surga meninggalkan ruang kosong yang kemudian diisi oleh komunitas beriman. Dengan bantuan Roh Kudus, komunitas beriman mengalami Allah sebagai presentia in absentia.
Dari perspektif Paskah, Allah yang mati dan naik ke surga meninggalkan ruang kosong yang kemudian diisi oleh komunitas beriman. Dengan bantuan Roh Kudus, komunitas beriman mengalami Allah sebagai presentia in absentia.
Meskipun Allah telah naik ke surga namun ia selalu hadir dan hidup dalam diri umat beriman lewat cara hidup mereka.
Secara antropologis, terjadilah Allah versi Feuerbach yang menganjurkan peralihan dari teologi kepada antropologi dan dalam term Levinas tentang wajah di mana Allah hanya bisa dijumpai dalam bentuk relasi dengan wajah yang lain, wajah orang asing, wajah korban yang jatuh ke tangan penyamun ketika turun dari Yerusalem ke Yerihko (Lukas 10:30-37).
Bereferensi pada kekosongan asali usai naiknya Allah ke surga, demokrasi radikal sebagai ruang kosong selalu mengandaikan kerja dari komunitas politik masyarakat sipil sebagai subjek warga negara. Meskipun demikian, argumentasi Feuerbach tentang peralihan dari teologi (filsafat) kepada antrolopogi, mengikuti Georg Lukás “menyebabkan manusia menjadi beku dalam objektivitas yang fix dan karena itu mengabaikan dimensi dialektis dan historis (Davis, 2009:6).
Logika PL juga terdapat dalam sejarah kehidupan bernegara di Indonesia. Pada masa otoritarian, pemimpin dimengerti sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kekuasaan dan hukum. Dengan kata lain, hukum adalah apa yang ia katakan dan lakukan. Saya teringat dengan pernyataan terkenal dari Raja Louis XVI di Prancis, “Negara adalah saya” sebagai ekspresi tak terpisahnya kekuasaan dan persona berbasiskan aktor.
Bereferensi pada kekosongan asali usai naiknya Allah ke surga, demokrasi radikal sebagai ruang kosong selalu mengandaikan kerja dari komunitas politik masyarakat sipil sebagai subjek warga negara. Meskipun demikian, argumentasi Feuerbach tentang peralihan dari teologi (filsafat) kepada antrolopogi, mengikuti Georg Lukás “menyebabkan manusia menjadi beku dalam objektivitas yang fix dan karena itu mengabaikan dimensi dialektis dan historis (Davis, 2009:6).
Logika PL juga terdapat dalam sejarah kehidupan bernegara di Indonesia. Pada masa otoritarian, pemimpin dimengerti sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kekuasaan dan hukum. Dengan kata lain, hukum adalah apa yang ia katakan dan lakukan. Saya teringat dengan pernyataan terkenal dari Raja Louis XVI di Prancis, “Negara adalah saya” sebagai ekspresi tak terpisahnya kekuasaan dan persona berbasiskan aktor.
Sementara itu, pada era reformasi (baca: demokrasi radikal), kekuasaan, mengutip Michael Foucault, bersifat tersebar dan tidak terpusat. Implikasinya, perbincangan tentang kekuasaan tidak lagi punya penanda yang tetap seperti negara, birokrasi, dan institusi formal lainnya, tetapi merasuk dalam keseharian hidup setiap orang. Singkatnya, kekuasaan menjadi rentan dan terlihat sejauh diisi oleh subject position warga negara dalam wacana tertentu, atau dalam bahasanya Žižek, “Help yourself and God will help you. Believe that God guides your hand, but act as if everything depends on you”! (Žižek, 2001:125-126).
Dengan momen kosongnya kekuasaan tersebut, tidak ada wacana yang mengklaim diri sebagai yang paling legitim dan absolut. Terjadi perlaihan dari transendensi kepada imanensi (dari Allah Bapa kepada Putera yang bangkit dalam persatuan dengan Roh Kudus) yang membawa implikasi emansipatoris di mana sekularisasi dilihat secara positif sebagai ada dalam dunia bersama Roh Kudus. Tepat pada level inilah, inkarnasi selalu membawa di dalam dirinya unsur lokalitas sebagaimana Allah hadir dalam lokalitas Yahudi.
Dengan momen kosongnya kekuasaan tersebut, tidak ada wacana yang mengklaim diri sebagai yang paling legitim dan absolut. Terjadi perlaihan dari transendensi kepada imanensi (dari Allah Bapa kepada Putera yang bangkit dalam persatuan dengan Roh Kudus) yang membawa implikasi emansipatoris di mana sekularisasi dilihat secara positif sebagai ada dalam dunia bersama Roh Kudus. Tepat pada level inilah, inkarnasi selalu membawa di dalam dirinya unsur lokalitas sebagaimana Allah hadir dalam lokalitas Yahudi.
Bertolak dari lokalitas dan partikularitas sebagai wujud runtuhnya metanarasi, inkarnasi merupakan inti terdalam demokrasi: “toleransi, non-otoritarian dan demokrasi masyarakat plural di Barat merupakan terjemahan kepada politik konkret dari struktur doktrin Kristen tentang mengasihi sesama (Žižek dalam Davies, 2009:256). Inilah inti dari konsep kenosis dalam kekristenan: pengosongan diri Allah dan kekuasaan.
Konsep tentang Manusia dan Subjek sebagai Sasaran Keselamatan
Dalam PL, keselamtan bersifat partikular dan esklusif, hanya dikhususkan kepada bangsa Israel (as chosen people). Di situ, dominasi kaum laki-laki sangat signifikan sebagai kelas yang paling berkuasa menentukan keselamatan bangsa. Akibatnya, manusia PL adalah manusia yang teralienasi karena mengandalkan apa yang disebut oleh Hegel dan Marx sebagai subjek moral dan karena itu dideterminasi oleh dunia objektif.
Sementara itu, pada PB, keselamatan menjangkau semua orang, tidak terbatas pada apakah orang Yahudi atau bukan, bersunat atau tidak. Ada upaya memberi tempat bagi “Other” yang secara eksplisit digambarkan dalam peristiwa “Perempuan Samaria”. Bahkan, dalam peristiwa kebangkitan, sosok pertama yang menerima kabar tersebut secara langsung dari Yesus adalah perempuan bernama Maria Magdalena. Itu berarti keselamatan bukan lagi sebuah kerja individual sebagaimana dalam PL melainkan kerja kolektif. Dikatakan demikian karena 'belief in God is not a singular or individual enterprise, but is intersubjective and communitarian' (Purcell, 2006:60).
Jika merujuk pada pemikir kristen Agustinus, terdapat kepercayaan bahwa ide tentang “Self” senantiasa terpisah sebelum beristirahat dengan damai dalam Allah. Bagi Agustinus, tidak ada subjek otonom atau 'cogito' sebagaimana dalam klaim Descartes, “I think, therefore I am”. Ada dua jenis implikasi pemahaman subjek cogito Descartes yakni pertama, yang seluruhnya terpusat di dalam dirinya sendiri (premis dasar dari liberalisme atau “kehendak berkuasa”-nya Nietzsche) dan kedua, subjek yang tampil melawan dunia ekstrenal sekaligus tak tampak (postmetafisika Levinnas, Derrida).
Sambil bereferensi pada kategori terakhir, manusia PB adalah manusia kasih yang berani hidup tanpa politik penandaan absolut dan selalu mengandalkan politik perjumpaan. Itulah alasan mengapa Lacan menegaskan bahwa kasih selalu adalah kasih kepada ‘yang lain’ sejauh karena kekurangan atau keterbatasannya (Žižek dalam Davies, 2009:39). Kesimpulan radikal ini menunjukkan bahwa jika kita mencintai Allah, artinya, seharusnya Allah dibayangkan sebagai sosok yang tidak sempurna dan punya banyak kekurangan, bahkan mengandung inkonsistensi di dalam diri-Nya sendiri. Kasih dalam pengertian ini selaras dengan definisi Derrida tentang hospitalitas sebagai tanggung jawab terhadap ‘yang asing’ dan tidak menyerang ketika mereka memasuki teritori orang lain (Derrida, 2007:2-6).
Era Orde Lama (ORLA) dan Orde Baru (ORBA) memosisikan subjek warga negara dari perspektif nasionalisme sempit sebagai wacana gerakan yang tak jarang terjebak pada logika etnosentrisme dan rasialisme. Di situ, proses saling mengesklusi dianggap sebagai cara paling ampuh mendefinisikan diri, kelompok, dan komunitas melalui frasa Soekarnoisme seperti “ganyang Malaysia” atau kelompok ultra-nasionalis melalui “NKRI Harga Mati”, “Pancasilais”, “Anti-PKI”, dan seterusnya.
Toleransi lalu dimengerti secara otomatis sebagai toleran terhadap sesam komunitas dan bukan terhadap “yang lain”, mereka yang asing. Dengan kata lain, menjadi warga negara tidak lagi didefinisikan berdasarkan darah (etnisitas) melainkan berdasarkan pengetahuan tentang batas negara. Merujuk pada tradisi Yahudi, orang dikonstitusikan melalui kekurangannya atas tanah, tentang territorial, di mana kekurangan ini dijelaskan kembali dalam bentuk hasrat absolut mengenai “Kedatangan Yerusalem” (Žižek, 2005:154). Logika kepemilikan atas teritori juga merambah dalam dunia politik di mana orang asing didefinisikan pertama-tama melalui tempat kelahirannya dan bukan kematiannya (Derrida, 2017:14).
Dengan perkembangan digitalisasi yang membuat batas-batas dunia menjadi kabur, logika pembedaan tersebut bekerja dalam domain ideologi. Respon datang dari demokrasi radikal yang menawarkan paradigma baru simetris dengan PB sebagai upaya memberikan tempat bagi “yang lain”, termasuk kaum perempuan, LGBT, dan seterusnya berdasarkan 'subject position'.
Di situ, yang lain dipandang legitimatte di dalam dirinya sendiri. Bagi Levinas, as soon as one faces the other person, the situation is at once ethical, and demands response and decision (Purcell, 2006: 34). Momen pengambilan keputusan itu merupakan momen etis dan menjadi inti berdemokrasi sebagaimana yang ditegaskan oleh Yesus sendiri, “Jika seseorang datang kepada-Ku dan tidak membenci ayahnya dan ibunya, istrinya dan anak-anaknya, saudara dan saudarinya, bahkan hidupnya sendiri, dia tidak layak menjadi murid-Ku” (Lukas 14:26).
Ada pembalikan total mengenai sesama manusia berdasarkan garis keturunan Yahudi kepada dimensi lain, “Lihatlah, inilah ibu dan saudara-saudari-Ku (Matius 12:46-50). Pernyataan ini mendekonstruksi norma sosial yang rigid tentang keluarga kepada kehidupan sosial yang lebih luas, dari grup partikular kepada universal.
Ada pembalikan total mengenai sesama manusia berdasarkan garis keturunan Yahudi kepada dimensi lain, “Lihatlah, inilah ibu dan saudara-saudari-Ku (Matius 12:46-50). Pernyataan ini mendekonstruksi norma sosial yang rigid tentang keluarga kepada kehidupan sosial yang lebih luas, dari grup partikular kepada universal.
Di sini, kasih mampu mengatasi serentak melampaui tegangan antara partikular dan universal. Hal yang sama juga diamanatkan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia (3:28). Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus.
Dengan demikian, iman menjadi, secara khusus jika diekspresikan dalam kasih, sebuah kondisi untuk mengerti bagaimana sebuah situasi dipahami, melampaui fantasi dan cara berpikir kita (Žižek, 2012:79). Iman, bagi Žižek, merupakan tindakan revolusioner, dalam kosa kata psikoanalisa sebagai trauma dan dalam istilah teologis sebagai sebuah mukjizat (2012:101).
Model Pendekatan yang Digunakan (Strategic Approach)
PL menekankan strategi pendekatan top-down di mana Allah sebagai otoritas yang memprakarsai projek keselamatan. Sementara itu, pada PB, dengan mengandalkan strategi horizontal (bukan bottom-up), keselamatan merupakan hasil akumulasi dari dialog dengan umat beriman berdasarkan latar belakang pendidikan (ahli Taurat), kelas (orang kaya), dan kultur (perempuan Samaria).
ORBA, melalui projek pembangunan bernama developmentalism, menjadikan relasi pusat dan daerah semata-mata berlangsung dari perspektif nasional. Meskipun reformasi berhasil mengubah ketimpangan struktural ini namun masih ada hal yang absen yakni struktur kesadaran mental sipil. Dengan kata lain, belum ada dialog yang komprehensif antara negara dan sipil. Mempertimbangkan kondisi seperti ini, muncul pertanyaan, bagaimana seharusnya gereja merumuskan model pendekatannya? Schmitt mengutip tulisan E. Piterson bertajuk Theologische Traktate demikian:
It is absolutely true that the church is therefore ambivalent. It is not a clearly defined religio-political entity, like the messianic kingdom of the Jews. On the onther hand, the church is not simply a purely spiritual entity in which concept such as politic and dominion are entirely prohibited, something which has restricted itself entirely to service. The intrinsic ambiguity of the church can be clarified trough the interpretation of empire and church. The ambiguity is caused by unbelief of Jews, which always enraged a moralist like Nietzsche about all Christian concepts (Schmitt, 1969:86-87).
Singkatnya, melalui penerimaan sakramen pembaptisan dan krisma, umat Kristen memeteraikan dirinya untuk siap melaksanakan kerja politis perutusan.
PL menempatkan hukum sebagai panglima dalam wujud Hukum Taurat. Selain bertendensi menjaga kohesivitas dan keteraturan, hukum bekerja dalam logika Hobbesian yakni merepresi subjektivitas. Itulah alasannya mengapa, istilah “ketakutan yang suci” pada Allah merupakan frasa kunci yang penting dalam PL di mana ketakutan dan kesucian berkelindan di dalam hukum. Sebaliknya, PB melepaskan ketergantungan berlebihan pada hukum dengan mereformulasikannya serentak mereaktivasi hukum lewat penambahan dimensi baru yakni kasih.
Kasih yang adalah hukum baru ini bukan dimaksudkan untuk menggantikan hukum yang lama melainkan menyempurnakan sekaligus melengkapi. Hal ini tersurat dalam pernyataan Yesus sendiri, “Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat” (Matius 5:18). Bahkan lebih tegas ditulis, “Lebih mudah langit dan bumi lenyap dari pada satu titik dari hukum Taurat batal (Lukas 16:17).
Pemujaan berlebihan nyaris menyerupai iman terhadap hukum, tampak dalam sistem pemerintahan otoriter bahkan dalam beberapa kasus tertentu, terdapat dalam sistem demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini. Sebagaimana ORBA menjadikan pembangunan sebagai panglima, pada masa ini, hukum diperlakukan serupa dan bukannya politik sebagai panglima.
Hukum dan Etika
PL menempatkan hukum sebagai panglima dalam wujud Hukum Taurat. Selain bertendensi menjaga kohesivitas dan keteraturan, hukum bekerja dalam logika Hobbesian yakni merepresi subjektivitas. Itulah alasannya mengapa, istilah “ketakutan yang suci” pada Allah merupakan frasa kunci yang penting dalam PL di mana ketakutan dan kesucian berkelindan di dalam hukum. Sebaliknya, PB melepaskan ketergantungan berlebihan pada hukum dengan mereformulasikannya serentak mereaktivasi hukum lewat penambahan dimensi baru yakni kasih.
Kasih yang adalah hukum baru ini bukan dimaksudkan untuk menggantikan hukum yang lama melainkan menyempurnakan sekaligus melengkapi. Hal ini tersurat dalam pernyataan Yesus sendiri, “Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat” (Matius 5:18). Bahkan lebih tegas ditulis, “Lebih mudah langit dan bumi lenyap dari pada satu titik dari hukum Taurat batal (Lukas 16:17).
Pemujaan berlebihan nyaris menyerupai iman terhadap hukum, tampak dalam sistem pemerintahan otoriter bahkan dalam beberapa kasus tertentu, terdapat dalam sistem demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini. Sebagaimana ORBA menjadikan pembangunan sebagai panglima, pada masa ini, hukum diperlakukan serupa dan bukannya politik sebagai panglima.
Hadir dengan dimensi baru, kasih sebagai aspek etis dari hukum berupaya menjawab ketakcukupan hukum positif dalam bentuk negosiasi diantara warga negara. Dengan kata lain, aspek etis mendekonstruksi klaim moral berlandaskan oposisi biner seperti “benar-salah”, “baik-buruk”, dan “hitam-putih”. Kasih merupakan satu-satunya cara menyelamatkan dimensi etis subjek warga negara yang cenderung mengandalkan hukum dan kehadiran negara sebagai satu-satunya otoritas yang mampu memecahkan segala persoalan hidup.
Dengan menafsir “Before the Law” dari The Trial karya Kafka, Žižek menjelaskan bahwa hukum membuat kita merasa bersalah tanpa kita tahu terhadap apa kita merasa bersalah (Žižek, 2005:164). Sebaliknya, hadirnya kasih merupakan upaya merevitalisasi hukum positif.
Dengan menafsir “Before the Law” dari The Trial karya Kafka, Žižek menjelaskan bahwa hukum membuat kita merasa bersalah tanpa kita tahu terhadap apa kita merasa bersalah (Žižek, 2005:164). Sebaliknya, hadirnya kasih merupakan upaya merevitalisasi hukum positif.
"If love is a disruptive force, it has the same qualities as law, but the law in Christianity means the law of justice and so is an act of solidarity".
Dengan demikian, hukum dalam Judaisme dan Kritianitas bukanlah legalitas melainkan solidaritas. ltulah alasannya mengapa kehadiran Yesus bukan untuk mengapus hukum melainkan meradikalisasinya (Sigurdson, 2012:72).
Hal yang sama juga dilakukan oleh Žižek ketika ia menafsir "Ethics and Infinity" karya Levinas dengan menegaskan bahwa, "ethics involves an asymmetric relationship in which I am always-already responsible for the Other, while politics is the domain pf symmetrical equality and distributive justice" (Žižek, 2005:149). Bagi Levinas, kata Žižek, etika bukan tentang hidup melainkan tentang sesuatu yang lebih dari hidup itu sendiri.
Hal yang sama juga dilakukan oleh Žižek ketika ia menafsir "Ethics and Infinity" karya Levinas dengan menegaskan bahwa, "ethics involves an asymmetric relationship in which I am always-already responsible for the Other, while politics is the domain pf symmetrical equality and distributive justice" (Žižek, 2005:149). Bagi Levinas, kata Žižek, etika bukan tentang hidup melainkan tentang sesuatu yang lebih dari hidup itu sendiri.
Apa yang gagal dielaborasi oleh Levinas adalah bahwa manusia dalam pemahamannya luput memperhatikan aspek yang bukan manusia. Sementara itu Adorno lebih sadar dengan hal ini ketika ia menjelaskan tentang konsekuensi dari definisi dominan tentang manusia yang berakibat pada esklusi terhadap ‘yang bukan manusia’. Dengan kata lain, jika hukum melulu bergantung pada logika oposisi biner dan moral (human-nonhuman), mengutip Adorno, ‘yang bukan manusia’ maka hal itu justru menjadi dalil bagi tindakan barbarianism.
(bersambung...)
Derrida, Jacques. Hospitality, Journal of the Theoretical Humanities, Volume 5, Nomor 3, Desember 2002. Teks ini juga merupakan paper Derrida dalam workshop di Bosphorus University, Istanbul 9-10 Mei 1997. Teks yang saja juga dipublikasikan di Cogito 85, 1999:17-44, (eds) Ferda Keskin dan Onay Sozer.
Purcell, Michael. Levinas and Theology. Cambridge: Cambridge University Press, 2006).
Sigurdson, Ola. Theology and Marxism in Eagleton and Žižek. New York: Palagrave Macmillan, 2012.
Žižek, Slavoj dan Milbank, John. The Monstrosity of Christ (Paradox or Dialectic?), edit. Creston Davis. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 2009.
Žižek, Slavoj; Santer, Eric L; Reinhard, Kenneth. The Neighbor: Three Inquiries in Political Theology. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2005.
Žižek, Slavoj. On Belief. London dan New York: Routledge, 2001.
Schmitt, Carl. Political Theology II (The Myth of the Closure of any Political Theology). Polity Press, 1969.
(bersambung...)
Referensi
Derrida, Jacques. Hospitality, Journal of the Theoretical Humanities, Volume 5, Nomor 3, Desember 2002. Teks ini juga merupakan paper Derrida dalam workshop di Bosphorus University, Istanbul 9-10 Mei 1997. Teks yang saja juga dipublikasikan di Cogito 85, 1999:17-44, (eds) Ferda Keskin dan Onay Sozer.
Purcell, Michael. Levinas and Theology. Cambridge: Cambridge University Press, 2006).
Sigurdson, Ola. Theology and Marxism in Eagleton and Žižek. New York: Palagrave Macmillan, 2012.
Žižek, Slavoj dan Milbank, John. The Monstrosity of Christ (Paradox or Dialectic?), edit. Creston Davis. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 2009.
Žižek, Slavoj; Santer, Eric L; Reinhard, Kenneth. The Neighbor: Three Inquiries in Political Theology. Chicago and London: The University of Chicago Press, 2005.
Žižek, Slavoj. On Belief. London dan New York: Routledge, 2001.
Schmitt, Carl. Political Theology II (The Myth of the Closure of any Political Theology). Polity Press, 1969.




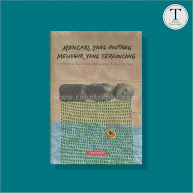
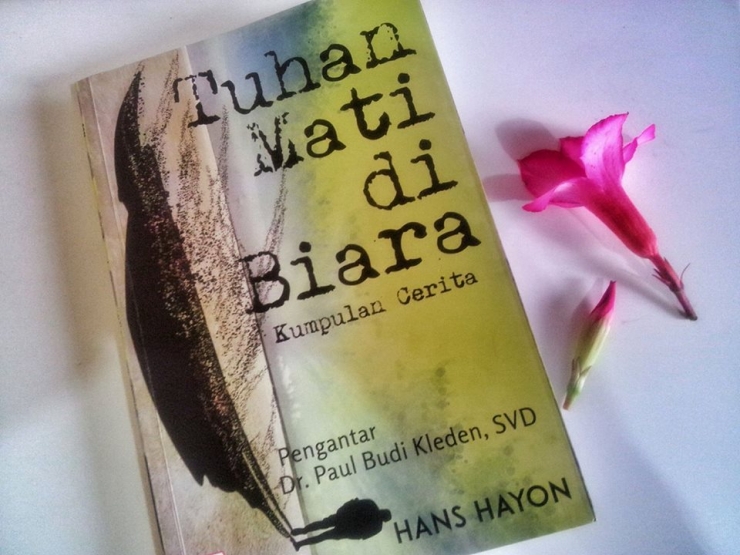

Post a Comment
Post a Comment