 |
| Ilutrasi makan bersama. Sumber Foto: Hendra. |
Sering disebut, aktivitas makan-makan merupakan bagian dari kebudayaan. Demikian juga sistem yang memproduksi makanan. Di balik upacara makan-makan, tersirat pembagian kerja (division of labor) antara produksi dan konsumsi: ada kelompok masyarakat yang menghasilkan jagung, beras, pisang, atau apa pun makanan yang Anda konsumsi.
Di sana juga ada penetapan protokol makan: kapan, di mana, bagaimana, dan untuk tujuan atau dalam konteks apa Anda makan. Bahkan, di sana juga tersembul dimensi religiositas: ada pemeluk agama yang puasa makan pada hari raya; atau ada penganut aliran kepercayaan yang haram mengonsumsi jenis makanan tertentu.
Tidak mengherankan jika Arthur Schopenhaur, filsuf Jerman itu mengatakan bahwa dirimu adalah apa yang engkau makan (you are what you eat).
Ada hubungan timbal balik dan saling memengaruhi antara makanan dan manusia. Sebuah hubungan intim yang pada abad ini telah dikomodifikasi, dibuat menjadi begitu asing, disingkirkan dimensi-dimensi luhur yang mahal ongkosnya.
Lalu terciptalah apa yang disebut oleh Jean Baudrillard sebagai masyarakat konsumsi (consumer society): sebuah kelompok masyarakat yang hanya tahu makan tapi tidak mengenal dari mana makanan itu berasal, dengan cara apa ia dihasilkan, berapa keringat dan biaya yang dihabiskan untuk menghasilkan makanan itu, konsekuensi apa saja yang ditimbulkan, dan apa jenis kepentingan yang sedang dilayani.
Jujur, kita bahkan tidak tahu dari mana sumber beras yang Anda makan dalam bentuk nasi, petani tembakau mana yang menghasilkan rokok yang Anda isap, nelayan daerah mana yang menangkap ikan yang Anda santap, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah sebuah sistem ekonomi yang berupaya membuat kabur relasi antara produksi dan konsumsi, sebuah relasi yang bagaimana pun juga menciptakan kebudayaan kita hari ini.
Itu berarti berbicara tentang aktivitas makan-makan dan apa apa yang kita makan, mewajibkan pengamatan dan pemahaman yang mendalam terkait biodiversitas atau keanekaragaman hayati yang menjadi sumber utama apa yang kita makan.
Disebut demikian karena mustahil ada makanan yang jatuh begitu saja dari langit. Oleh karena itu, bagaimana pun juga terasa sangat mustahil membahas tentang makanan terpisah dari eksistensi keanekaragaman hayati.
Sebelum melanjutkan pembahasan ini, sejujurnya, tulisan ini lahir berkat mengikuti pertemuan online, Kamis (14 April 2022) bersama teman-teman Eco Blogger Squad dengan pembicara dari Yayasan KEHATI Mbak Rika. Dalam sesi pemaparan materinya, Mbak Rika menjelaskan secara terperinci tentang Keanekaragaman Hayati baik secara global maupun nasional, potensi pemanfaatan dan tantangan yang dihadapi ke depan. Dibahas dari sudut pandang krisis iklim, Mbak Rika menekankan tiga hal: Pertama, definisi dan peta sebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Kedua, potensi pemanfaatan keanekaragaman hayati. Ketiga, apa yang harus dilakukan.
Nah, dalam rangka memudahkan pembahasan, tulisan ini mengambil contoh diversifikasi pangan sebagai pintu masuk diskusi yang coba membahas tentang peralihan mode produksi dan konsumsi di Indonesia baik sebagai akibat tata kelola atau kebijakan politik pangan maupun sebagai efek terdekat dari adanya perubahan iklim.
Apa Itu Keanekaragaman Hayati?
Semangat dasar dalam pembahasan tentang diversifikasi pangan tentu saja bertolak dari kata “diverse” pada biodiversitas atau keanekaragaman (hayati). Disebut demikian karena antara diversifikasi pangan dan keanekaragaman hayati, terdapat hubungan yang saling terkait. Pemahaman yang baik tentang keanekaragaman hayati akan mengantar orang pada kesadaran akan tata kelola pangan yang beranekaragam. Ini hubungan sebab akibat yang sangat sederhana. Namun sejak tahun 1992, ketika ditemukan bahwa ada penurunan kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati maka dibentuk konvensi yang mempertemukan banyak negara untuk membahas dan memperbaiki masalah ini.
Implikasi terdekat dapat diamati melalui apa yang dilakukan oleh Yayasan KEHATI, sebuah lembaga nirlaba yang ada di Indonesia memiliki fokus serius pada upaya menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana hibah bagi pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
Dalam rangka memerinci sub ini, keanekaragaman hayati dapat dibagi ke dalam beberapa tingkatan antara lain:
Pertama, ekosistem sebagai tingkatan di mana makhluk hidup dapat berinteraksi dengan lingkungan fisiknya. Padang rumput, hutan hujan tropis, gambut, mangrove, terumbu karang, dan sebagainya merupakan beberapa contohnya.Spesies, tingakatan kedua sebagai keragaman jenis organisme yang menempati suatu ekosistem yang mempunyai ciri yang berbeda satu dengan yang lain.Genetik, sebagai tingkatan ketiga, yakni keanekaragaman individu di dalam suatu jenis yang disebabkan oleh perbedaan genetis antarindividu. Contoh perbedaan genetis dapat dilihat misalnya varietas mangga, pisang, dan sebagainya.
Mengapa Penting?
Pembahasan ini sangat penting karena beberapa alasan, sebagai berikut:
Pertama, kesadaran selalu lahir dari pengetahuan. Itulah mengapa ketidaktahuan merupakan problem yang serius bagi bangsa ini. Dengan kata lain, kita perlu mengetahui dan menyadari manfaat dari keanekaragaman hayati yang ada di negara ini. Pengetahuan itu tentu saja termasuk ancaman kepunahan yang pada akhirnya memengaruhi keseluruhan tatanan ekosistem.
Kedua, menyadari betapa pentingnya topik ini, perlu ada riset yang dilakukan terus menerus secara berkala. Sayangnya, seperti yang dikatakan oleh Mbak Riska, kompleksitas objek kajian dan keterbatasan finansial masih menjadi kendala serius yang mesti segera diatasi.
Ketiga, jasa keanekaragaman hayati ada begitu banyak. Beberapa diantaranya yakni menjadi sumber daya air, menjaga kesuburan tanah, menyerap karbondioksida, menjaga stabilitas iklim, menjadi sumber makanan dan obat, pertanian, peternakan, industri, dan lain sebagainya. Singkatnya, eksistensi keanekaragaman hayati menjamin adanya keseimbangan kehidupan manusia dengan alam secara keseluruhan.
Keempat, dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, kelompok masyarakat adat memainkan peran sentral. Disebut demikian karena kelompok masyarakat adat memiliki pemahaman yang lebih lengkap dan holistik tentang lingkungan dan alam, bahkan mengembangkan kehidupan mereka selaras dengan alam. Tidak mengherankan jika dalam konteks pandemi misalnya, salah satu dari antara mereka, misalnya Suku Baduy, sanggup bertahan.
Meskipun demikian, dicatat beberapa tantangan serius yang dihadapi berkaitan dengan keanekaragaman hayati, antara lain:
Pertama, tantangan langsung yang terdiri atas hilang atau berkurangnya habitat keanekaragaman hayati karena adanya pembukaan lahan baru untuk perkebunan, pemukiman, industri tambang, dan bentuk-bentuk pembangunan lain yang tidak peka dengan lingkungan hidup. Kedua, polusi udara juga menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan terganggunya eksosistem keanekaragaman hayati. Ketiga, selain itu, meningkatnya populasi manusia juga menjadi salah satu pengaruh paling signifikan. Hal ini tentu saja mencakup eksploitasi atau praktik perdagangan satwa yang dilakukan secara massif.
Kedua, tantangan tidak langsung atau sebagai pemicu awal hilangnya keanekaragaman hayati antara lain: kebijakan atau pola pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, maraknya gaya hidup konsumerisme di mana apa yang kita konsumsi tidak mendukung keberlanjutan lingkungan. Untuk menguji argumen ini, Anda bisa mengecek apa produk kosmetik yang Anda pakai, apakah buku yang Anda baca berbahan dasar kertas yang berasal dari kertas daur ulang, dan seterusnya.
Di samping itu juga, terbatasnya jenis atau varietas yang dibudidayakan di Indonesia misalnya, membuat kebijakan pangan di negara ini sangat bergantung pada kebijakan impor. Selain itu, punahnya keanekaragaman hayati juga disebabkan oleh adanya intervensi berlebihan produk berbahan kimia yang terdapat dalam pupuk, pakan, dan sebagainya.
Flores Timur: Sebuah Ilustrasi
Sudah banyak dicatat dalam berbagai penelitian bahwa perubahan suhu global memengaruhi keanekaragaman hayati dengan dampak dan skala kerusakan berganda, baik terhadap gen dan komunitas, maupun ekosistem (Permesan, 2006; Bellard, dkk., 2012). Hal ini dapat diamati di lingkungan sekitar. Di bidang pertanian dan pangan misalnya, terjadi penurunan 10 persen panen padi pada setiap kenaikan suhu satu derajad celcius suhu rata-rata. Bahkan tangkapan ikan di Indonesia juga mengalami penurunan hingga 40 persen karena banyak jenis ikan bermigrasi mencari iklim yang lebih sejuk atau terlanjur punah akibat perubahan iklim.
Dampak ini diperburuk dengan tata kelola atau kebijakan pangan yang tidak peka dengan kondisi geografis suatu daerah. Swasembada pangan yang diterjemahkan dalam kebijakan politik pembangunan sebagai berasnisasi adalah salah satu dari sekian banyak contohnya. Namun, tanpa harus meletakkan kesalahan tunggal pada rezim ORBA, pola konsumsi masyarakat pada pangan lokal seperti pola beras-umbi-umbian atau beras-jagung-umbi, ditinggalkan berubah ke pola tunggal beras (Rachman, 2001). Padahal, jauh sebelum itu, masyarakat di daerah kering rata-rata memakan jagung atau ubi-ubian sebagai makanan pokok karena tidak banyak membutuhkan air.
Kebiasaan itu secara evolutif membentuk pola makan khas dan unik di pelbagai daerah: gaplek (Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur), sagu (Maluku, Papua), jagung (Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara), sorgum (Nusa Tenggara Timur), talas dan ubi jalar (Papua) sebagai bahan pangan baru warga selama bertahun-tahun (Khudori, 2010). Karakteristik semacam ini mesti terakomodir dalam register keputusan politik ketika menanggulangi kasus rawan pangan.
Selain mencegah rawan pangan semata-mata melalui bantuan raskin, diversifikasi pangan merupakan cara kita melepaskan ketergantungan pada kebiasaan impor. Ini dibuat dengan cara mengembangkan aneka pangan lokal yang dapat diproduksi sendiri ketimbang melakukan impor. Gandum misalnya, dapat disubtitusi dengan ubi jalar, dan gembili. Oleh sebab itu, perlu ditetapkan zona agroekologi lahan-lahan pertanian-pangan mengingat setiap tanaman memiliki perbedaan tingkat kesesuaian lahan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam poin keempat pada bagian awal tulisan ini.
Bertolak dari kenyataan itulah, dan diperparah dengan kondisi meningkatnya angka stunting di NTT, diberlakukan pembaruan kebijakan pangan di provinsi kepulauan dengan curah hujan rendah itu. Di Kabupaten Flores Timur tempat saya berasal misalnya, kerja sama mewujudkan hal itu melibatkan banyak komponen masyarakat baik dari pemerintah dan agama maupun tokoh masyarakat setempat.
Awal mula munculnya kebijakan tersebut tentu bukan karena adanya kesadaran mengenai pentingnya diversifikasi pangan. Sebaliknya, problem stunting-lah yang menjadi pemicu awalnya. Diketahui secara umum bahwa berdasarkan hasil Pantauan Status Gizi (PSG) 2018 prevalensi stunting bayi berusia di bawah lima tahun (Balita) Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 42,7%”. Artinya, empat dari 10 anak NTT mengalami stunting. Dari angka tersebut 22,3 % terdiri dari bayi dengan kategori pendek sedangkan 18 % sisanya berada pada kategori sangat pendek. Padahal angka rata-rata nasional stunting hanya sebesar 29,6%.
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 juga menunjukkan sebanyak 269.658 balita dari 633.000 balita di NTT tercatat mengalami stunting (berbadan pendek) dan 75.960 balita di antaranya mengalami wasting (kurus). Tingginya penderita balita stunting di NTT disebabkan oleh faktor gizi yang sangat kurang. Banyak ibu-ibu saat hamil tidak memberikan asupan gizi yang baik sehingga melahirkan anak dengan postur tubuh kerdil. Bertolak dari kenyataan itulah, digalakan diversifikasi pangan melalui pembudidayaan sorgum yang telah lama hilang dari peradaban Lamaholot, Flores Timur.
“Iya sejak awal memang pengembangan pangan sorgum ini juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah ini. Salah satu kampanye kami untuk pencegahan stunting adalah konsumsi sorgum karena khasiat sorgum yang bernilai gizi tinggi. Kami punya istilah Solor yang artinya Sorgum-Kelor. Saat ini kami terus memberdayakan para petani untuk mulai mengembangan tanaman sorgum sebagai pangan alternatif pengganti beras dan jagung. Konsumsi sorgum dan kelor sangat baik untuk pencegahan stunting," kata Bupati Flores Timur, Anton Hadjon, Jumat (17/4) dikutip dari Media Indonesia.
Lalu, mengapa kebijakan politik pangan sangat penting dibahas di sini?
Jawaban cepat yang dapat saya berikan yakni karena pangan lokal sebenarnya bukanlah hal baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia baik itu di NTT maupun di daerah lain. Itu berubah karena intervensi berlebihan dari negara yang mengatur apa yang perlu dan tidak perlu diproduksi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui skema permintaan ekspor-impor.
Dikutip dari laman KEHATI misalnya, ditemukan bahwa jejak kultural sorgum di NTT khususnya Flores menunjukkan bahwa tanaman ini sudah lama menjadi bagian dari masyarakat bahkan sebelum tahun 1900-an. Asumsi itu diperkuat dengan argument dari botanis Jerman yang bekerja untuk VOC Georg Eberhard Rumphius yang meneliti keragaman hayati di Ambon sejak tahun 1954. Dalam catatannya yang kemudian dibukukan, ia menyebutkan, “sorgum telah tumbuh di mana-mana di Indies (Nusantara)”, namun pada umumnya hanya ditanam di pinggir ladang (Rumphius, 1747:195). Bahkan di buku tersebut juga diceritakan tentang bukti sejarah bertani di Nusantara, terutama di Pulau Jawa.
Akhirnya, budaya makan-makan yang kita hidupi setiap saat hendaknya dipahami dan dihayati secara kritis. Disebut demikian karena tidak ada aktivitas konsumsi tanpa produksi dan tidak ada aktivitas produksi tanpa mengenal dan memahami potensi dan ancaman kepunahan keanekaragaman hayati di Indonesia.
#Ecobloggersquad






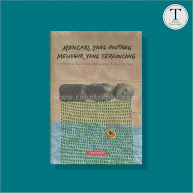
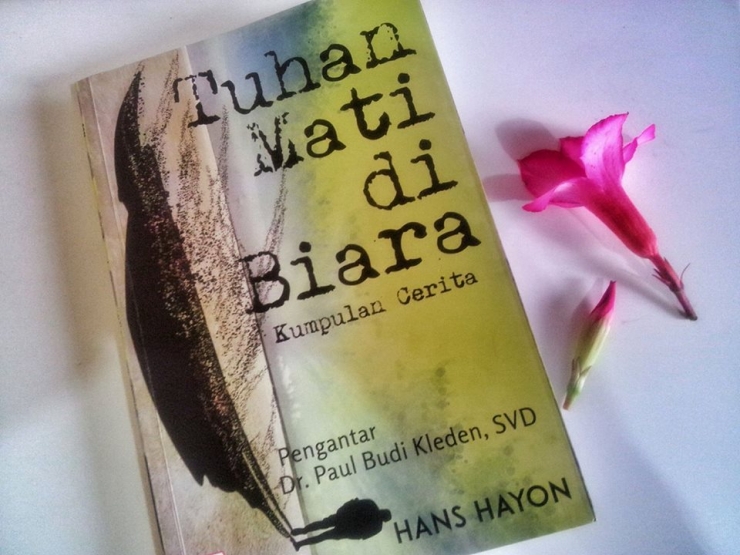

Post a Comment
Post a Comment